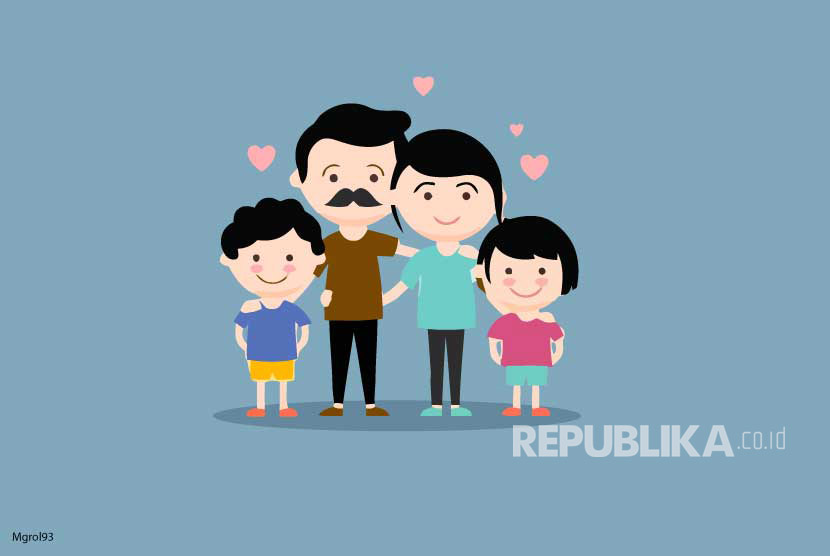Karunia Kalifah Wijaya
Karunia Kalifah Wijaya
Agama | 2025-03-31 07:46:00
"Manusia paling kuat adalah ia yang mampu mengendalikan dirinya sendiri." Meskipun kutipan ini bukan berasal dari Friedrich Nietzsche, ia mencerminkan salah satu esensi utama filsafatnya, bahwa kekuatan sejati bukan tentang dominasi atas orang lain, melainkan tentang kemampuan seseorang untuk menaklukkan dirinya sendiri. Jika kita melihat Idul Fitri sebagai "hari kemenangan," maka pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah kemenangan atas apa?
Setiap tahun, umat Islam merayakan Idul Fitri sebagai puncak dari ibadah Ramadan, sebuah bulan yang dikatakan menjadi ajang pembentukan ketakwaan, pengendalian diri, dan peningkatan spiritualitas. Namun, apakah perayaan ini benar-benar mencerminkan kemenangan sejati atas ego dan hawa nafsu, atau justru menjadi ritual seremonial yang dijalani tanpa kesadaran mendalam? Apakah Idul Fitri menjadi simbol transformasi diri yang otentik, atau justru menjadi rutinitas yang memperkuat mentalitas kepatuhan tanpa pertanyaan kritis?

Idul Fitri dan Dilema Moralitas Budak vs Moralitas Tuan
Salah satu kritik terbesar Nietzsche terhadap agama dan moralitas tradisional adalah kecenderungannya untuk menciptakan moralitas budak, sebuah mentalitas yang didasarkan pada kepatuhan, ketundukan, dan penerimaan pasif terhadap aturan yang ditetapkan oleh otoritas eksternal. Dalam karyanya On the Genealogy of Morality, ia membedakan antara moralitas budak dan moralitas tuan.
Moralitas budak lahir dari rasa ketidakberdayaan dan ketakutan. Ia menekankan nilai-nilai seperti kerendahan hati, pengorbanan, dan kepatuhan sebagai bentuk kompensasi atas kelemahan individu. Sebaliknya, moralitas tuan berakar pada keberanian untuk menciptakan nilai-nilai sendiri, keberdayaan, dan kemandirian eksistensial.
Dalam konteks Idul Fitri, pertanyaannya menjadi: Apakah Idul Fitri yang kita jalani adalah ekspresi dari moralitas budak atau moralitas tuan? Jika seseorang berpuasa dan merayakan Idul Fitri hanya karena tekanan sosial, karena "sudah seharusnya", tanpa memahami makna personalnya, maka Nietzsche akan melihatnya sebagai bentuk moralitas budak. Idul Fitri dalam kasus ini tidak lebih dari sekadar ritual yang diulang setiap tahun tanpa adanya refleksi mendalam.
Sebaliknya, jika seseorang menjalankan Ramadan dengan kesadaran penuh sebagai ajang menaklukkan diri, dan merayakan Idul Fitri sebagai manifestasi kemenangan sejati atas dirinya sendiri, maka perayaan ini menjadi ekspresi moralitas tuan. Individu ini tidak hanya mengikuti ritual secara mekanis, tetapi benar-benar menciptakan makna bagi dirinya sendiri, menjadikan Ramadan sebagai perjalanan spiritual yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat.
Nietzsche akan mengkritik mereka yang menjalankan Idul Fitri secara mekanis, tanpa refleksi kritis terhadap makna di baliknya. Dalam pandangannya, agama yang dijalankan hanya berdasarkan dogma dan kebiasaan tanpa adanya internalisasi dan penciptaan makna pribadi hanya akan memperkuat mentalitas kepatuhan buta, yang pada akhirnya melemahkan eksistensi manusia.
Idul Fitri dan Amor Fati: Mencintai Perjalanan, Bukan Sekadar Menikmati Akhir
Konsep lain dalam filsafat Nietzsche yang relevan untuk memahami Idul Fitri adalah Amor Fati, sebuah gagasan tentang menerima dan mencintai takdir dalam segala aspeknya, baik suka maupun duka. Nietzsche tidak hanya menyerukan penerimaan terhadap kehidupan, tetapi juga mengajak manusia untuk mengafirmasi setiap pengalaman sebagai bagian yang tak terpisahkan dari eksistensi.
Dalam konteks Idul Fitri, Amor Fati mengajarkan bahwa puasa Ramadan bukan sekadar kewajiban yang harus ditanggung demi mencapai Idul Fitri, tetapi sebuah perjalanan yang harus dijalani dengan kesadaran penuh dan kecintaan akan prosesnya.
Banyak orang melihat Ramadan sebagai beban yang harus ditanggung selama sebulan, dengan Idul Fitri sebagai pelepasannya. Jika seseorang hanya menahan lapar dan haus tanpa memahami esensinya, lalu merayakan Idul Fitri sebagai "akhir dari penderitaan," maka ia gagal menjalankan Amor Fati.
Bagi Nietzsche, individu yang kuat adalah mereka yang tidak hanya menerima penderitaan, tetapi juga mengafirmasi penderitaan sebagai bagian dari pertumbuhan dan penciptaan diri. Jika Ramadan dimaknai sebagai latihan mental dan spiritual, bukan sekadar serangkaian larangan, maka Idul Fitri bukanlah "akhir dari penderitaan," melainkan simbol dari perjalanan eksistensial yang telah dijalani dengan kesadaran penuh.
Kemenangan Sejati atau Sekadar Euforia Sesaat?
Nietzsche menggambarkan kehidupan sebagai sebuah perjuangan untuk menegaskan keberadaan dan kekuatan diri, sebuah konsep yang ia sebut sebagai Will to Power. Kehendak untuk berkuasa dalam pemikirannya bukan berarti dominasi atas orang lain, melainkan kehendak untuk melampaui keterbatasan diri sendiri dan menciptakan nilai baru.
Jika Idul Fitri dipahami dalam perspektif Will to Power, maka pertanyaannya menjadi apakah Idul Fitri merupakan bukti bahwa kita telah menguasai diri, ataukah justru menjadi ajang kembali ke kebiasaan lama? Ramadan seharusnya menjadi latihan bagi manusia untuk menaklukkan ego, hawa nafsu, dan berbagai keterbatasannya. Jika setelah Idul Fitri seseorang kembali pada pola hidup lama tanpa adanya perubahan mendasar, maka sejatinya ia belum mengalami kemenangan sejati.
Nietzsche akan mengkritik keras mereka yang hanya berpuasa secara fisik tetapi tidak secara mental. Mereka yang menahan lapar tetapi tetap dikuasai oleh kebiasaan lama, baik dalam pola pikir, tindakan, maupun relasi sosial, tidak benar-benar mengalami transformasi.
Will to Power dalam konteks Idul Fitri adalah tentang bagaimana seseorang benar-benar mengambil kendali atas dirinya sendiri dan menjadikan Ramadan sebagai titik balik yang berkelanjutan. Perayaan ini bukan sekadar momentum sesaat, tetapi sebuah bukti bahwa seseorang telah melampaui dirinya yang lama dan menciptakan versi dirinya yang lebih kuat.
Sekadar Ritual atau Kemenangan Eksistensial?
Nietzsche menolak keberagamaan yang dijalankan tanpa kesadaran dan refleksi. Jika Idul Fitri ingin bermakna dalam perspektifnya, maka ia harus menjadi lebih dari sekadar perayaan. Ia harus menjadi momen afirmasi diri, di mana seseorang benar-benar keluar dari Ramadan sebagai individu yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih berdaya.
Jadi, pertanyaannya kembali pada kita apakah Idul Fitri yang kita rayakan benar-benar mencerminkan kemenangan atas diri sendiri, atau hanya sekadar rutinitas tahunan yang dijalani tanpa makna? Nietzsche akan menantang kita untuk menjawabnya dengan jujur dan lebih dari itu, untuk membuktikannya dalam kehidupan yang kita jalani setelah hari raya berlalu.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 1 day ago
6
1 day ago
6