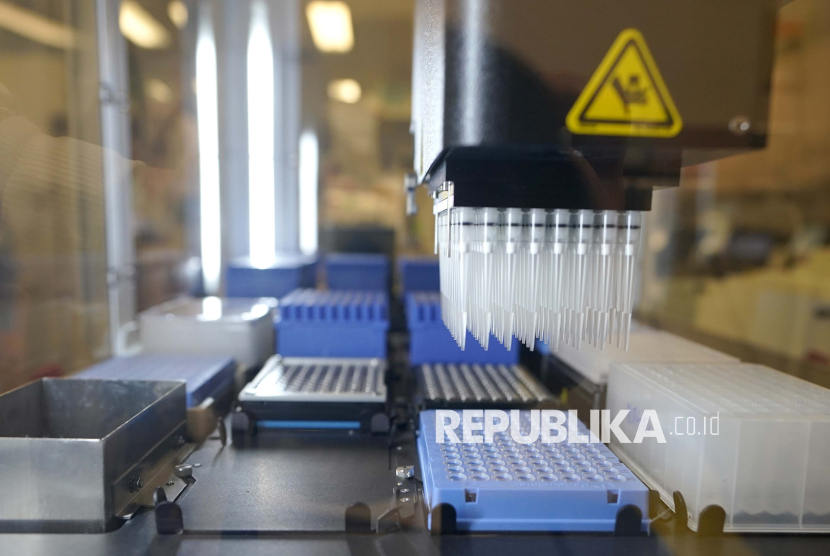Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Yang Hilang dari Kampus. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Foto ilustrasi Catatan Cak AT: Yang Hilang dari Kampus. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Sungguh, negeri ini sedang diuji bukan hanya dengan bencana alam, tapi juga dengan badai sunyi di dalam kepala generasi mudanya.
Bagaimana mungkin, dua mahasiswa dari dua kampus berbeda, di dua kota berjauhan, memilih jalan yang sama: terjun dari ketinggian, seolah ingin menembus langit lebih cepat dari doa orang tuanya.
Yang satu di Bali, yang satu lagi di Solo. Jarak ribuan kilometer, tapi waktu dan cara mereka mengakhiri hidup nyaris serupa.
Seakan ada koreografi gaib yang mempermainkan nalar kita. Seakan malaikat pencabut nyawa punya cara sendiri mengajari manusia soal hidup dan mati.
Baca juga: FH UI Gelar The 7Th International Conference on Law and Government in a Global Context 2025
Namun, yang menyesakkan dada: keduanya mahasiswa/i perguruan tinggi. Bahkan satunya dari Fakultas Ushuluddin dan Dakwah. Ya, ia dari kampus Islam negeri, tempat di mana ayat diajarkan bukan cuma di lidah tapi mestinya juga di hati.
Tentu saja seluruh kampus gempar dihadapkan pada kasus yang begitu miris dan menyayat kesadaran.
Bagaimana mungkin sang mahasiswi memilih loncat dari lantai lima kampus yang setiap paginya dipenuhi lantunan basmalah? Bukankah di sana para dosen yang doktor dan profesor menanamkan iman, tawakal, dan sabar sebagai pondasi akidah? Apa yang meleset? Di mana retak itu bermula?
Fenomena ini tak bisa lagi kita bungkus dengan kalimat: “Sedang depresi. Sedang berobat.” Ah, kalimat semacam ini sudah jadi mantra klise yang dipakai setiap kali kita tak sanggup memahami luka yang tak tampak.
Padahal, di balik istilah medis itu ada hutan rimba persoalan yang lebih dalam. Bisa jadi itu berupa kehilangan makna, keletihan eksistensial, keringnya kasih, dan terputusnya dialog antara jiwa dan Tuhannya.
Baca juga: Efisiensi, Dari 1.044 Perusahaan BUMN, BP Danantara akan Pangkas Jadi 240 Perusahaan
Para psikolog agama menyebutnya spiritual emptiness— kekosongan spiritual yang diam-diam membunuh rasa percaya diri dan makna hidup seseorang. Ketika iman kehilangan rasa, ayat hanya jadi bacaan tanpa getaran, dan ibadah jadi rutinitas tanpa makna.
Ulama klasik seperti Imam al-Ghazali sudah memperingatkan sejak abad ke-11: hati yang tak lagi merasa dekat dengan Allah Swt akan mencari pelarian pada hal-hal yang paling absurd, termasuk melukai diri sendiri.
Tapi bukankah banyak kondisi zaman ini memang sedang menghapus rasa? Kita hidup di era di mana kesedihan difilter seperti selfie, dibungkus dengan video, dan depresi dipublikasikan agar dikomentari.
Anak muda diajari cara menaklukkan dunia, tapi tak pernah diajari bagaimana berdamai dengan kegagalan. Mereka bisa membuat presentasi dengan Canva, tapi tak tahu cara mempresentasikan luka hatinya kepada Tuhan.
Dalam kitab al-Munqidz min al-Dhalal, al-Ghazali menulis: “Jiwa yang tercerabut dari maknanya ibarat burung kehilangan sarangnya, ia akan terus terbang tanpa arah, hingga jatuh karena lelah.”
Mungkin begitulah jiwa dua mahasiswa itu: burung-burung muda yang kehilangan arah, melayang di langit kampus dengan kepala penuh teori, tapi dada kosong dari makna. Ia datang ke kuliah, tapi memilih melemparkan diri dari ketinggian tingkat lima bersama kursi kuliahnya.
Pihak kampus bilang, si mahasiswi sudah mendapat pendampingan psikolog dan psikiater. Itu baik, tapi barangkali belum cukup. Karena luka jiwa bukan sekadar urusan serotonin, tapi juga urusan sujud yang kehilangan air mata.
Kampus modern kita rajin menanam IPK, tapi lupa menyiram iman; sibuk membangun laboratorium, tapi lupa memperkuat ruang batin.
Baca juga: Kemenag Rilis Data Sebaran Calhaj Depok 2026, Capai 1.291 Orang yang Tersebar di 11 Kecamatan
Cobalah kita tengok Jepang, negeri dengan teknologi sekelas dewa tapi juga angka bunuh diri setinggi langit. Mereka sudah lama sadar bahwa spiritual care adalah kebutuhan dasar, bukan pelengkap.
Di beberapa universitas Jepang, ada “ruang hening” di mana mahasiswa bisa duduk diam, merenung, berdoa, atau sekadar menangis tanpa dihakimi. Bandingkan dengan kampus kita yang ruang doanya pun kadang lebih sibuk dipakai rapat dosen.
Tragedi ini harus jadi tamparan kolektif. Bahwa pendidikan tinggi kita terlalu tinggi, tapi hati mahasiswanya justru rendah diri. Kita sibuk menyiapkan mereka jadi change maker, tapi lupa menjadikan mereka soul keeper.
Mungkin, ini bukan hanya kisah dua nyawa yang hilang dengan cara tragis, tapi dua tanda peringatan dari langit. Bahwa iman dan akal, agama dan psikologi, harusnya tidak saling bersaing, tapi saling menolong.
Baca juga: Festival El Dia de la Hispanidad, Cita Rasa Hispanik: Menikmati Rasa, Mengenal Bahasa
Sebab kalau mahasiswa Ushuluddin pun sudah kehilangan ushul (dasar), kepada siapa lagi kita berharap membenahi dakwah manusia modern yang kini bahkan tak tahu bagaimana mencintai dirinya sendiri?
Kadang, tragedi memang datang untuk mengingatkan: jangan-jangan yang benar-benar terjun bukan hanya dua mahasiswa itu, tapi juga kita semua. Kita terjun pelan-pelan ke jurang ketidakpedulian, setiap kali melihat ada anak muda menjerit minta tolong dengan cara diam. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 20/10/2025

 10 hours ago
7
10 hours ago
7