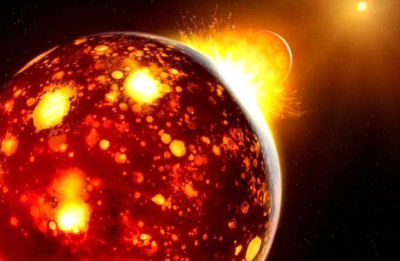Oleh Ahmadie Thaha, Kolumnis
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekarang ini, layar-layar media Barat dan lini masa media sosial kita dipenuhi satu lakon yang dimainkan berulang-ulang: Iran digambarkan seolah sedang di ambang kejatuhan. Judul-judul berita menjerit tentang “demonstrasi besar-besaran”, armada Amerika “bergerak ke Teluk”, dan “rezim yang goyah”.
Kalau tak hati-hati, kita bisa mengira Teheran sudah seperti rumah yang pintunya copot dan gentengnya beterbangan. Padahal, ketika angka dibuka — angka yang biasanya alergi terhadap drama — yang berdemo itu hanya ribuan dari sekitar 90 juta penduduk: nol koma nol sekian persen. Persis seperti menyimpulkan sebuah stadion runtuh hanya karena satu penonton batuk di tribun timur.
Di sinilah teknik lama itu bekerja: framing. Dalam literatur komunikasi politik, ini bukan hal baru. Noam Chomsky dan Edward Herman sejak lama menyebutnya sebagai manufacturing consent — cara membentuk persetujuan publik melalui seleksi fakta, penekanan tertentu, dan pengaburan konteks.
Kita disuguhi potongan gambar, lalu diminta menelan keseluruhan cerita. Kita diperlihatkan kerumunan, tanpa skala; disodori kata “meluas”, tanpa proporsi. Yang ramai bukan realitas di lapangan, melainkan gema di ruang redaksi dan algoritma.
Narasi itu terasa makin janggal ketika dibandingkan dengan cermin di hadapan mereka sendiri. Demonstrasi besar di Tel Aviv, protes berkepanjangan di Prancis, bahkan kerusuhan di kota-kota Amerika — semuanya jarang diberi baju “negara di ambang runtuh”.
Lucu, kata seorang teman di grup, betapa cepatnya mereka melihat bara di halaman tetangga, sambil menyembunyikan api di dapur sendiri. Maka publik Indonesia, yang kenyang menonton sandiwara geopolitik sejak Irak hingga Venezuela, cenderung mengangkat alis: Iran terlalu besar untuk dipatahkan dengan sekadar headline.
Yang sering luput dari sorotan adalah pembedaan yang dibuat Iran sendiri antara protes dan kerusuhan. Dalam banyak pernyataan resminya, Ayatullah Ali Khamenei menegaskan protes sah sepanjang tidak berubah menjadi kekerasan bersenjata dan perusakan. Bahkan ada fatwa yang menegaskan: protes boleh, kerusuhan dilarang.
Ini bukan retorika kosong. Rekaman di beberapa kota menunjukkan aparat mengawal demonstran tak bersenjata; yang diminta hanya satu: jangan hancurkan properti publik. Bagi negara yang sering dicap anti-demonstrasi, praktik ini justru terasa ironis — seolah-olah “otoritarian” itu lebih fasih membedakan hak sipil dan sabotase dibanding banyak negara yang mengaku “mercusuar demokrasi”.
Tentu, bukan berarti Iran tanpa problem. Ekonomi mereka tercekik, justeru karena sanksi Barat; fluktuasi nilai tukar membuat para pedagang pasar — kelompok yang historically menjadi tulang punggung Republik Islam — resah. Ketika pedagang berkata, “Kami tak bisa berbisnis dalam ketidakpastian kurs,” itu bukan propaganda; itu logika dagang.
Khamenei sendiri mengakui keberatan itu sebagai protes yang dibenarkan. Namun, di saat yang sama, ia mengingatkan adanya aktor-aktor yang menyamar sebagai pedagang, menyelipkan slogan anti-Islam, anti-Iran, dan anti-Republik Islam — garis tipis yang memisahkan kritik kebijakan dari operasi destabilisasi.
Banyak analis keamanan menyebut demonstrasi ini “terorganisir”: informasi dan gambar dikirim ke luar secara teratur melalui jalur komunikasi Starlink yang perangkatnya diselundupkan secara masif, sebagian peserta dilatih, tidak sepenuhnya spontan.
Dalam kacamata intelijen, protes semacam ini bukan sekadar ekspresi, melainkan juga “alat ukur” untuk membaca jaringan agen dan simpul pengaruh di dalam negeri — sejenis rontgen politik menjelang kemungkinan eskalasi.
Maka ketika video seorang gadis Iran membakar foto Netanyahu, Maryam Rajavi, Reza Pahlavi, dan Masih Alinejad, lalu mengangkat potret Khamenei sebagai bentuk dukungan, kita melihat satu hal: medan opini di Iran tidak searah seperti yang disederhanakan di luar.

 1 month ago
80
1 month ago
80