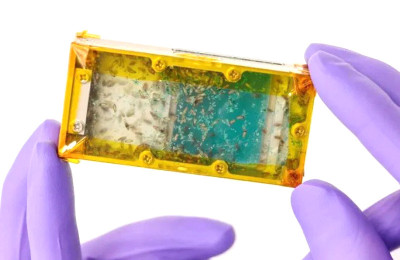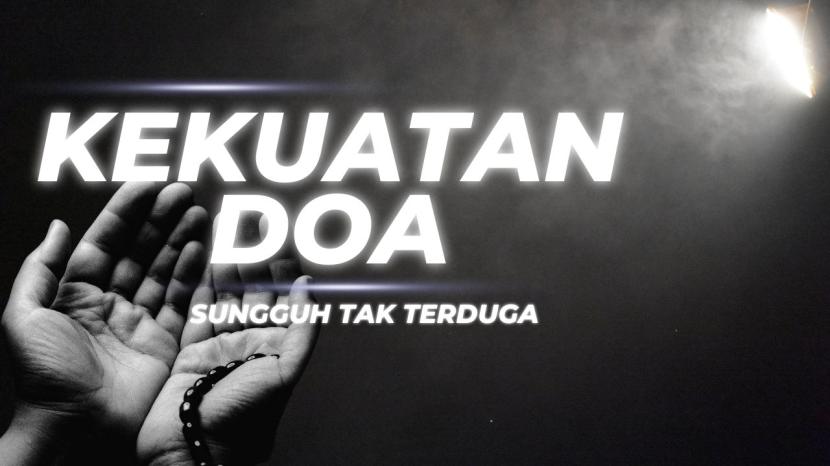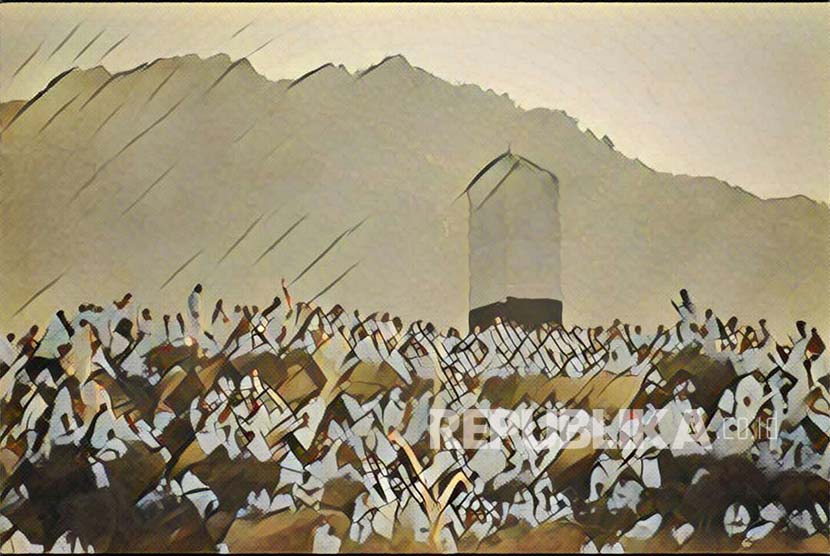Oleh : Letjen TNI Mohamad Hasan, Komandan Kodiklat TNI AD
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ruang digital hari ini bukan lagi sekadar “media sosial”; ia telah menjadi ruang hidup tempat kita bekerja, berbelanja, belajar, membentuk opini, bahkan menentukan sikap politik. Lebih dari 80 persen penduduk Indonesia kini terhubung ke internet; survei APJII 2025 mencatat penetrasi mencapai 80,66 persen atau sekitar 229 juta jiwa.
Dalam ekosistem yang luas dan cair ini, generasi Milenial dan Gen Z tulang punggung bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045 tumbuh sebagai digital natives yang menghirup dan mengembuskan informasi saban detik. Ruang digital yang luas dan dinamis ini sudah selayaknya dimasuki unsur bela negara untuk menjawab keresahan publik yang khawatir nasionalisme dan kecintaan pada negara tergerus disinformasi, hoaks, ujaran kebencian dan pengaruh asing yan bebas keluar masuk di ruang digital.
Keresahan yang Nyata
Dinamika terkini yang terjadi di ruang digital Indonesia sudah sangat berwarna dan mewarnai kehidupan anak-anak bangsa. Berbagai unggahan peristiwa dan cerita yang tersajikan di ruang digital adalah gambaran umum bagaimana publik berekspresi dengan bebas, kebebasan ini menghasilkan nilai-nilai berbeda satu sama lain, kemudian menciptakan berbagai pendapat, komentar dan reaksi yang beragam sesuai dengan opini yang muncul di benak orang yang membaca atau menonton unggahan tersebut. Kondisi ini juga menciptakan keresahan akan dampak yang tercipta dari berwarnanya nilai yang dihasilkan. Ada tiga sumber keresahan publik yang makin terasa :
Pertama, kebenaran yang “ditawar” algoritma. Platform dirancang untuk memaksimalkan waktu tonton dan interaksi. Akibatnya, konten yang memicu emosi, marah, cemas, takjub sering terdorong naik, sementara konten yang akurat namun “kurang sensasional” tenggelam. Di Indonesia, 57 persen warga mengaku memperoleh berita dari media sosial bukan dari situs media arus utama. Ini membuat proses pembentukan opini amat dipengaruhi kurasi mesin dan influencer ketimbang jurnalisme.
Kedua, ekonomi validasi. Budaya likes, share, comment menciptakan kebutuhan konstan akan pengakuan. Validasi sosial itu legit, tetapi ketika menjadi ukuran tunggal harga diri, ia mudah digiring untuk kepentingan komersial maupun politik. Maka, yang “benar” sering kalah oleh yang “ramai”.
Ketiga, arus mis/disinformasi yang makin canggih. Pemerintah sendiri beberapa kali menekan platform besar untuk memperkuat moderasi, setelah muncul kasus disinformasi (termasuk deepfake) yang memicu keresahan publik. Di saat bersamaan, regulasi ekosistem berita digital juga terus bergeser dari wacana kewajiban berbagi nilai ekonomi berita hingga standar usia minimum pengguna media sosial untuk melindungi anak.
Semua ini terjadi di tengah struktur demografi yang muda: Gen Z saja berjumlah sekitar 71,5 juta jiwa (±27 persen populasi), mengalahkan jumlah Milenial. Ketika ruang hidup mereka dominan digital, maka bela negara pun harus menemukan bentuknya yang digital. Era digital telah mengubah fundamental cara hidup berbangsa dan bernegara. Generasi Milenial (66,82 juta pemilih) dan Gen Z (46,8 juta pemilih, 75 juta populasi total) di Indonesia menghadapi tantangan unik sebagai digital natives yang harus menerapkan nilai-nilai kebangsaan di ruang digital. Dengan penetrasi internet nasional mencapai 80,66 persen dan durasi online rata-rata 8+ jam per hari, generasi ini memerlukan panduan komprehensif untuk mengimplementasikan bela negara di era digital.
Berdasarkan data dari Newzoo, pada tahun 2024 pengguna ponsel pintar di seluruh dunia mencapai 7,21 milyar dan Indonesia menduduki peringkat ke 4 dengan 187,7 juta pengguna ponsel pintar dari sekitar 275,5 juta penduduk Indonesia atau lebih kurang 68,1 persen. BPS mencatat pada tahun 2024 bahwa pengguna telepon seluler (HP) di Indonesia mencapai sekitar 82,05 persen dari penduduk usia 5 tahun ke atas dalam 3 bulan terakhir. Di sisi lain, penggunaan internet tercatat 72,78 persen pada populasi yang sama. Sementara itu, data dari awal tahun 2025 menunjukkan jumlah pengguna media sosial Indonesia sebanyak 143 juta identitas pengguna aktif, yang setara dengan sekitar 50,2 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 285 juta jiwa di awal tahun 2025.
Dari statistik ini, kita bisa melihat gambaran bahwa hampir seluruh manusia remaja hingga dewasa di Indonesia memiliki ponsel pintar dan memiliki akses terhadap banyak sekali informasi yang beredar dalam genggamannya. Kita bisa membayangkan derasnya arus informasi yang mengalir dan masuk ke dalam alam pikiran kita setiap detiknya. Di sisi lain, UNESCO pada September tahun 2025 mengeluarkan data statistik tentang literasi orang dewasa (15+) di tingkat global. Rilis tahun 2025 menggunakan data paling mutakhir tahun 2024. Tingkat melek huruf orang dewasa dunia: 88 persen (tahun data 2024). Gen-Z (15–24): 93 persen. Jumlah orang dewasa yang belum melek huruf: 739 juta (2024). Masih menurut data tersebut, dari 208 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-100 dengan literasi 95,44 persen dan ternyata posisi Indonesia masih kalah dengan negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina 96,62 persen di posisi ke-88, Brunei urutan ke-86 dengan 96,66 persen dan Singapura urutan ke-84 dengan 96,77 persen.
Bagi kita bangsa Indonesia, statistik tersebut menunjukkan sebuah ironi yang perlu diwaspadai. Di satu sisi Indonesia menjadi salah satu negara pengguna ponsel pintar terbesar di dunia, namun disisi yang lain kondisi literasinya masih tergolong rendah. Artinya bahwa besarnya arus informasi yang masuk ke critical thinking) dalam setiap individu manusia di Indonesia tidak dibentengi oleh kemampuan literasi (yang memadai. Jelas ini merupakan celah yang wajib diwaspadai, karena sangat besar potensi terjadinya bahaya akibat disinformasi dan misinformasi maupun keterpengaruhan terhadap aplikasi-aplikasi berbahaya yang begitu mudah tersebar. Ancaman digital yang dihadapi meliputi penyebaran hoaks, radikalisme online, cybercrime, disinformasi, dan invasi budaya asing yang bertentangan dengan karakter bangsa Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara dengan tingkat kerentanan serangan siber tertinggi di Asia Tenggara, dengan 877.316 dari 22,6 juta perangkat dikategorikan berisiko tinggi.
Bela Negara: Mandat Luhur di Seluruh Ruang Hidup
Secara hukum, bela negara adalah mandat konstitusional yang dijalankan melalui pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara mencakup manusia, alam, hingga sarana-prasarana agar siap dipakai demi kepentingan pertahanan. Ini ditegaskan dalam UU No 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, yang juga mengakui peran komponen cadangan dan pendukung. Dengan kata lain bela negara harus hidup di seluruh ruang kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di ruang digital. Di ruang digital, bela negara bukan berarti memobilisasi warganet untuk perang siber, apalagi memburu lawan politik. Esensinya tetap sama: merawat akal sehat publik, memperkuat kohesi sosial, melindungi infrastruktur informasi, dan memastikan ekosistem digital berpihak pada kebenaran serta kepentingan nasional. Bela negara digital didefinisikan sebagai tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI untuk menangkal ancaman di ruang digital demi menjaga kedaulatan, persatuan dan kesatuan keselamatan bangsa.
Bela negara di ruang digital bukan mengangkat senjata, melainkan mengangkat standar kebenaran. Ia tidak memerangi manusia, ia menangkis manipulasi. Ia tidak membungkam lawan, ia membuka pikiran kawan dan lawan dengan data. Di sini, patriotisme bukan pekik, melainkan kebiasaan: memverifikasi sebelum berbagi, menjaga sesama dari hoaks, dan merayakan Indonesia lewat karya dari video satu menit sampai dashboard data. Ketika generasi muda menjadi kurator kebenaran dan produsen solidaritas, bonus demografi berubah menjadi dividen kebangsaan. Ruang digital pun menjelma penangkal, benteng, sekaligus studio kreatif tempat nasionalisme bertumbuh sunyi, tekun, dan berkelanjutan.
Empat “Retakan” yang Harus Ditutup
Pertama, Retakan literasi: banyak yang mahir memakai aplikasi, tetapi belum piawai menimbang kredibilitas sumber, memahami context collapse, atau membaca isyarat manipulasi (judul clickbait, narasi biner “kami vs mereka”, false context).
Kedua, Retakan kepercayaan: survei global memperlihatkan kepercayaan pada berita cenderung stagnan dan rendah; audiens muda makin mengandalkan kreator dan algoritma untuk kurasi.
Ketiga, Retakan insentif: platform memberi penghargaan atas keterlibatan, bukan kebenaran. Tanpa intervensi kebijakan dan inovasi model bisnis berita, insentif ini tak berubah.
Keempat, Retakan tata kelola: regulasi perlindungan anak dan moderasi konten masih berkejaran dengan inovasi teknologi (misalnya deepfake). Pemerintah merespons, tetapi butuh arsitektur kolaborasi yang lebih lincah dengan platform dan masyarakat sipil.
Jalan Keluar: “Bela Negara di Ruang Digital”
Berikut kerangka kerja praktis yang bisa segera kita jalankan tanpa menunggu segalanya sempurna.
Pertama adalah Kecakapan Warga (Civic Digital Literacy). Terdiri dari Saring sebelum sebar: reverse image search, membaca tentang sumber, cek tanggal, dan kenali teknik disinformasi (mislabel, cheapfake, deepfake); Jejak digital beretika: pegang tiga sumbu fakta, konteks, sopan santun; dan Imunitas algoritmik: sadar bahwa feed adalah filter bubble. Ikuti media kredibel, abaikan sumber toksik, dan rutinkan “diet digital” untuk menyehatkan kurasi.
Selanjutnya Tanggung Jawab Platform. Terdiri dari Desain aman-by default: reporting yang mudah, rate limit untuk konten viral berisiko, dan friction sebelum reshare konten sensitif; dan Transparansi kurasi untuk konten berita dan politik, serta kemitraan yang adil dengan penerbit.
Ketiga, Penegakan dan Tata Kelola Publik. Terdiri dari Regulasi adaptif: misalnya batas usia media sosial dan sanksi pada platform yang lalai menekan disinformasi; Pusat Respons Cepat Hoaks lintas Kemenhan, Kominfo, TNI, Polri, BSSN, komunitas fact-checker dengan protokol rilis klarifikasi yang ramah share.
Keempat, Gerakan Masyarakat: “Ronda Digital”. Terdiri dari Komunitas kampus, pesantren, karang taruna, dan tech clubs menjadi posko literasi dan early warning hoaks lokal; dan Tantangan kreatif: bikin konten debunk 60 detik, duet klarifikasi, micro-podcast jurnalisme warga.
Terakhir, Ekosistem Talenta: “Kader Bela Negara Digital”. Terdiri dari Program fellowship untuk Gen Z/Milenial: open-source intelligence dasar, fact-checking, keamanan siber personal, dan etika AI; Hackathon “Code for Tanah Air”: alat cek konteks otomatis, deteksi deepfake ringan, dan dashboard misinformasi daerah; dan Magang lintas media–kampus–startup, sehingga kurir kebenaran tak kalah gesit dari kurir clickbait.
Mengapa Ini Mendesak?
Karena arus lebih menentukan bentuk tepi sungai ketimbang batu. Dengan penetrasi internet yang telah melampaui 80 persen dan konsumsi berita yang bergeser ke media sosial, arus informasi itulah yang sehari-hari mengikis atau menguatkan kesadaran bela negara kita. Bonus demografi tak otomatis menjadi dividen; ia bisa menjadi liabilitas bila generasi muda terseret polarisasi, scam, radikalisasi, dan apatisme digital. Sebaliknya, ketika generasi ini menjadi kurator kebenaran, produsen solidaritas, dan penjaga etika di dunia maya, mereka menjelma komponen pendukung pertahanan yang efektif sejalan dengan ruh UU 23/2019.
Bela negara di ruang digital tidak romantik. Ia teknis, sehari-hari, dan kadang sunyi: mengaktifkan 2FA, menolak judul yang menghasut, membaca sampai tuntas, memperbaiki teman yang keliru tanpa mempermalukannya, dan memberi engagement pada konten yang benar walau tak “viral”. Negara wajib hadir dengan kebijakan yang melindungi; platform wajib jujur dengan desainnya; kampus, sekolah, dan media wajib memperbarui kurikulumnya; dan kita semua terutama Milenial dan Gen Z wajib menata ulang kompas: viral bukan kebenaran, ramai bukan realitas, dan cinta tanah air berarti berdisiplin menjaga akal sehat bersama.
Bayangkan sistem imun nasional digital yang sunyi, konsisten, dan efektif. Sistem ini akan berperan sebagai sejumlah hal:
Penangkal (imunitas pengetahuan): Literasi informasi, verifikasi cepat (saring sebelum sebar), memahami cara kerja algoritma, dan kebiasaan menjaga “diet digital” agar feed tidak menjadi ruang gema.
Benteng (ketahanan dan keselamatan): Keamanan identitas dan perangkat (kata sandi kuat, 2FA), perlindungan data pribadi, kebijakan moderasi yang adil, serta standar transparansi platform—agar arus informasi tidak mudah disabotase dan warga merasa aman bersuara.
Ruang kreatif (narasi kebangsaan): Produksi konten positif dan relevan: sains populer berbahasa lokal, cerita sejarah, budaya Nusantara, kisah inspiratif layanan publik, micro-podcast kebangsaan, short video klarifikasi hoaks, open-data storytelling kemajuan daerah semua menyuburkan rasa memiliki pada Indonesia.
Bela negara di dunia maya adalah etik dan kreatif, bukan militeristik. Ia menguatkan cinta tanah air lewat disiplin informasi, keamanan digital, dan penciptaan narasi positif agar arus informasi mengarah ke persatuan, bukan perpecahan. Menuju Indonesia Emas 2045, bela negara di ruang digital adalah investasi paling sunyi namun paling menentukan. Jika ruang hidup kita sehat, republik kita kuat.

 1 month ago
62
1 month ago
62