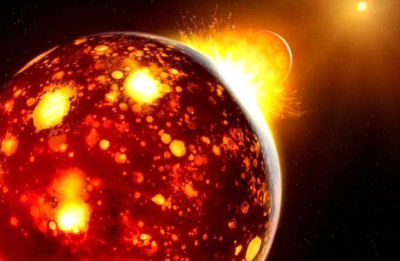Oleh : Fahmi Salim, Direktur Al-Fahmu Institute
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Salah satu medan paling menentukan dalam perjuangan Palestina hari ini bukan hanya politik dan militer, tetapi medan fatwa dan mimbar dakwah. Di ruang inilah kesadaran umat dibentuk: siapa yang dianggap zalim, siapa yang dinormalisasi, dan di mana posisi keadilan diletakkan.
Karena itu, ketika fatwa dan dakwah justru dipakai untuk melunakkan bahkan membenarkan relasi dengan penjajah Israel, bahayanya jauh melampaui satu keputusan politik. Ia menyentuh fondasi moral dan metodologi keilmuan Islam itu sendiri.
Fenomena yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir adalah maraknya narasi keagamaan yang membingkai normalisasi penjajahan sebagai pilihan syar‘i, dengan dalih kemaslahatan, stabilitas, atau perdamaian. Narasi ini sering dibungkus dengan istilah fikih yang terdengar shahih, namun jika ditelusuri lebih dalam, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Alquran dan kaidah fikih yang mapan.
Di forum Konferensi Internasional Ketiga bagi Para Dai dan Alumni Syariah yang diselenggarakan oleh Lembaga Amanah Al-Aqsha yang saya hadiri terdapat satu sesi panel membahas tema: Membongkar Narasi Fatwa dan Dakwah yang Menormalisasi Penjajahan. Dalam seminar ini, Dr Jamal Abdul Sattar, Sekretaris Jenderal Ikatan Ulama Ahlussunnah dan pakar syariah dari Universitas Al-Azhar Mesir, mengupas secara kritis fenomena normalisasi penjajahan melalui fatwa dan dakwah, serta menjelaskan bagaimana sebagian konsep fikih dan dalil syar‘i disalahgunakan—dicabut dari konteksnya—untuk menghasilkan pembenaran keagamaan atas relasi dengan penjajah Zionis.
Fatwa dan Keberpihakan terhadap Keadilan
Dalam tradisi Islam, fatwa bukan sekadar jawaban hukum teknis, melainkan instrumen moral untuk menegakkan keadilan. Alquran dengan tegas melarang sikap condong kepada kezaliman, sekecil apapun bentuknya: “Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.” (QS. Hud: 113).
Normalisasi penjajahan—baik dalam bentuk kerja sama politik, keamanan, maupun ekonomi—adalah bentuk kecenderungan terhadap kezaliman struktural. Ia bukan posisi netral. Karena itu, kaidah fikih menegaskan:
الرضا بالظلم ظلم
Merelakan kezaliman adalah kezaliman itu sendiri.
Fatwa yang membiasakan hubungan dengan penjajah berarti menggeser batas antara adil dan zalim, serta menjadikan kezaliman sesuatu yang “dapat diterima secara bertahap”. Inilah bahaya paling serius dari normalisasi berbasis fatwa.
Penyalahgunaan Konsep Darurat dan Maslahah
Salah satu argumen utama dalam fatwa pro-normalisasi adalah klaim darurat politik dan maslahah. Padahal, dalam ushul fikih, darurat memiliki syarat ketat. Alquran menegaskan bahwa darurat hanya berlaku dalam kondisi terpaksa dan tidak melampaui batas (QS. Al-Baqarah: 173).
Para ulama merumuskan kaidah penting:
الضرورة تُقدَّر بقدرها
Darurat diukur sesuai kadarnya.
Dan juga:
ما جاز لعذر بطل بزواله
Sesuatu yang dibolehkan karena uzur menjadi batal ketika uzur itu hilang.
Normalisasi dengan penjajah Israel bersifat permanen, terstruktur, dan sistemik, bukan kondisi sementara. Ia juga menghilangkan hak pihak lain—yakni rakyat Palestina. Karena itu, klaim darurat dalam konteks ini gugur secara metodologis.
Demikian pula konsep maslahah. Alquran menjadikan keadilan sebagai pilar utama syariat:
“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil.” (QS. An-Nahl: 90).
Maslahah yang mengorbankan keadilan dan korban penjajahan bukan maslahah yang diakui syariat. Dalam ushul fikih, ini disebut:
مصلحة ملغاة – maslahah yang tertolak.
Manipulasi Narasi Damai dan Ahlul Kitab
Narasi lain yang sering digunakan adalah bahwa Israel adalah “tetangga” dan “Ahlul Kitab” sehingga layak dinormalisasi. Ini adalah pengaburan konteks yang serius. Alquran memang membuka ruang perdamaian:
“Jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya.” (QS. Al-Anfal: 61).
Namun ayat ini bersyarat, bukan mutlak. Perdamaian harus menghentikan agresi dan mengakui hak. Ketika penjajahan, perampasan tanah, dan pembunuhan masih berlangsung, maka perintah yang didahulukan justru adalah pembelaan terhadap yang tertindas:
“Mengapa kamu tidak berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang tertindas…” (QS. An-Nisa: 75).
Status Ahlul Kitab tidak pernah dalam Alquran dijadikan alasan untuk melegitimasi kezaliman. Menyebut penjajah sebagai “tetangga” sambil menutup mata dari realitas kolonialisme adalah manipulasi moral yang berbahaya.
Boikot dan Larangan Menguatkan Kezaliman
Sebagian fatwa bahkan memandang boikot ekonomi sebagai “tekanan politik yang memalukan”. Padahal, Alquran secara tegas melarang kerja sama dalam dosa dan permusuhan:
“Dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Ma’idah: 2).
Kaidah fikih menyatakan:
الوسائل لها أحكام المقاصد
Sarana mengikuti hukum tujuan.
Jika tujuan ekonomi penjajah adalah menopang kezaliman, maka setiap sarana yang menguatkannya ikut terlarang. Dalam kerangka ini, boikot bukan tindakan ekstrem, melainkan bentuk minimal dari amar ma’ruf nahi munkar.
Kerja Sama Keamanan dan Konsep Wilayah
Normalisasi juga sering masuk melalui dalih kerja sama keamanan. Alquran memberi peringatan keras terkait menjadikan pihak yang memusuhi umat sebagai pelindung politik:
“Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai wali dengan meninggalkan orang-orang beriman.” (QS. Ali ‘Imran: 28).
Kerja sama keamanan yang merugikan umat dan memperkuat penjajah termasuk bentuk wilayah politik terlarang, bukan sekadar hubungan sipil biasa.
Fikih Pesanan dan Krisis Otoritas Ulama
Dari sini lahir fenomena yang oleh banyak ulama disebut “fikih pesanan”: fatwa yang menyesuaikan dalil dengan kepentingan kekuasaan dan dana. Seolah-olah muncul kaidah fikih baru: addolarot tubiihul mahzuuraaat-- dolar menghalalkan yang haram. Padahal, dalam fikih berlaku prinsip:
الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا
Hukum berputar bersama illatnya.
Selama illat penjajahan dan kezaliman masih ada, maka hukum menolaknya tetap berlaku. Ketika fatwa kehilangan keberpihakan pada yang tertindas, maka yang rusak bukan hanya keputusan hukum, tetapi otoritas moral ulama itu sendiri.
Akibatnya, otoritas ulama terkikis. Umat menjadi skeptis. Fatwa tidak lagi dipandang sebagai suara nurani syariat, tetapi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan.
Damai Bukan Berarti Menyerah
Penting ditegaskan: Islam bukan agama konflik, tetapi agama keadilan. Perdamaian dalam Islam bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan tegaknya hak dan berhentinya kezaliman. Alquran memerintahkan damai, tetapi juga menegaskan larangan mendukung kezaliman.
Normalisasi dengan penjajah yang belum menghentikan penjajahan bukan perdamaian, melainkan legitimasi ketidakadilan. Ini perbedaan mendasar yang sering sengaja dihapus dalam dakwah pro-normalisasi.
Tanggung Jawab Ulama dan Dai
Dalam situasi seperti ini, ulama dan dai memikul tanggung jawab besar: Menjaga kemurnian metodologi fikih, Menolak kooptasi politik terhadap mimbar, Berpihak pada korban, bukan pada penindas.
Mimbar bukan ruang netral. Ia selalu berpihak—pertanyaannya, berpihak kepada siapa? Kepada keadilan atau kepada kekuasaan?
Penutup
Membongkar narasi fatwa pro-normalisasi penjajah Israel bukanlah sikap politis sempit atau ekstremisme agama. Ia adalah upaya menyelamatkan marwah fatwa, metodologi fikih, dan fungsi dakwah. Alquran menegaskan bahwa Allah berpihak pada yang tertindas (QS. Al-Qashash: 5), dan fatwa yang sejati harus berada di barisan yang sama.
Sejarah Islam mencatat bahwa ulama yang setia pada keadilan sering kalah secara politik, tetapi menang secara moral. Di tengah arus normalisasi, menjaga kejernihan fatwa adalah bagian dari jihad intelektual dan etis—agar agama tetap menjadi cahaya pembebasan, bukan alat legitimasi penjajahan.

 2 months ago
154
2 months ago
154