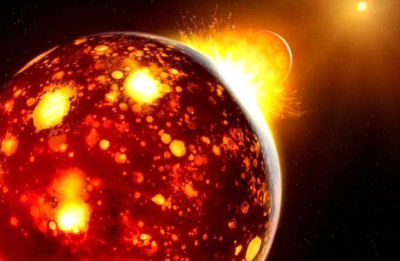REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Indonesia perlu memperkuat ambisi dan implementasi aksi iklim setelah Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belem, Brasil. Meskipun COP30 menghasilkan dokumen Gotong Royong Global atau Global Mutirão, lembaga ini menilai komitmen internasional masih belum cukup untuk menahan laju krisis iklim.
IESR menyoroti lemahnya kesepakatan global untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan belum konkretnya komitmen pendanaan iklim. Inisiatif baru seperti Global Implementation Accelerator (GIA) dan Belém Mission to 1.5 dinilai belum mampu memenuhi urgensi penurunan emisi pada dekade kritis ini. Aspek transisi berkeadilan juga belum mendapat porsi kuat dalam dokumen akhir.
Catatan kritis juga diberikan kepada Indonesia. Delima Ramadhani, Koordinator Kebijakan Iklim IESR, mengatakan ambisi dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC) yang diperbarui pada 2025 belum mencerminkan temuan mendesak dari First Global Stocktake. Padahal, mekanisme ini menegaskan perlunya penurunan emisi global 43 persen pada 2030 dan 60 persen pada 2035 dibanding level 2019.
Analisis Climate Action Tracker menunjukkan komitmen global saat ini masih membawa dunia pada risiko kenaikan suhu 2,6 derajat Celsius di akhir abad.
Dalam SNDC, Indonesia menetapkan target 2035 tanpa memperbarui target 2030, yang menurut IESR penting sebagai tindak lanjut hasil Stocktake. Delima menilai transparansi meningkat tetapi ambisi jangka pendek belum menunjukkan perbaikan nyata. Target puncak emisi pada sektor energi yang dipatok pemerintah pada 2038 dinilai terlalu lambat dibanding kebutuhan global. “Ini menunjukkan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia masih bergantung tinggi karbon,” ujar Delima, Senin (8/12/2025).
Indonesia juga belum menyatakan komitmen eksplisit untuk phase-out bahan bakar fosil, termasuk batu bara yang tetap dipertahankan melalui teknologi clean coal dan co-firing biomassa. IESR menekankan bahwa penurunan emisi Indonesia masih bertumpu pada sektor kehutanan dan lahan, sementara emisi di sektor energi justru berpotensi meningkat.
Di luar penyerapan dari sektor FOLU, emisi nasional diproyeksikan naik hingga 98 persen dalam skenario tidak bersyarat, atau 54–84 persen di atas emisi 2019 dalam skenario bersyarat.
Manajer Diplomasi Iklim dan Energi IESR Arief Rosadi menilai Indonesia memiliki momentum politik yang kuat untuk berperan sebagai pemimpin negara Global South dalam memperkuat aksi iklim pasca-COP30. Hal ini selaras dengan berbagai pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan energi terbarukan dan ambisi nasional menuju 100 persen energi terbarukan pada 2035.
Arief menyebut ada tiga langkah yang perlu ditempuh. Pertama, memperjuangkan isu iklim dan transisi energi di forum internasional sembari memastikan kebijakan domestik mencerminkan ambisi tinggi. Kedua, menerjemahkan keputusan multilateral menjadi kemitraan konkret dan mendorong implementasi lintas negara.
"Indonesia memiliki rekam jejak sebagai pemimpin dalam menyediakan fondasi proses global, baik saat menjadi host COP-13 yang menghasilkan Bali Roadmap, G20 Chairmanship (2022) yang melahirkan Bali Compact dan Bali Energy Transition Roadmap, serta pada saat keketuaan ASEAN yang menghasilkan ASEAN Strategy for Carbon Neutrality,” ujar Arief.
Langkah ketiga adalah mengamplifikasi keputusan dan inisiatif yang mendorong energi terbarukan, termasuk gagasan “roadmap on transition away from fossil fuel” untuk dipromosikan di berbagai forum multilateral. Menurut IESR, langkah tersebut penting agar arah transisi global tetap terjaga dan sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius.

 2 months ago
93
2 months ago
93