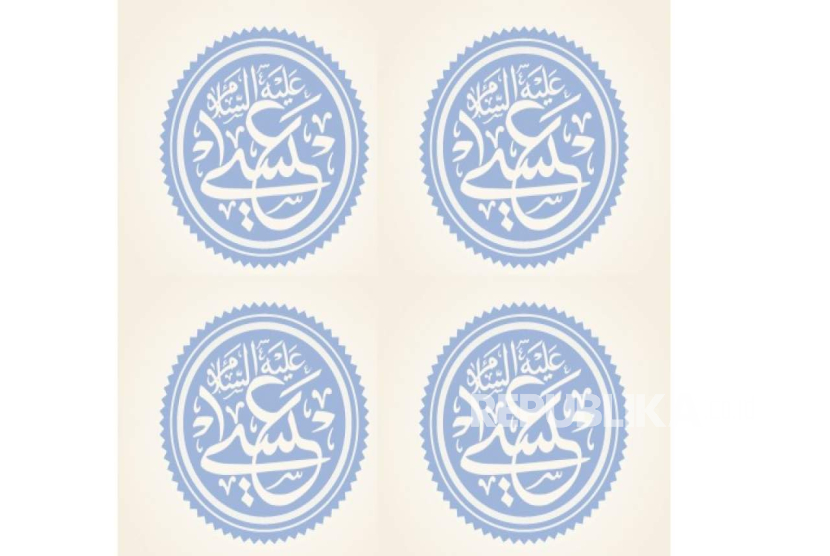REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gagasan memasukkan anak-anak “nakal” ke barak militer untuk dididik sedianya bukan barang baru. Di tengah epidemi tawuran yang melanda Jakarta pada 1990-an silam, hal serupa pernah dijalankan. Apakah cara itu kemudian terbukti efektif?
Pada awal hingga pengujung dekade 1990-an itu, jalan-jalan di Jakarta laiknya medan perang bagi anak-anak SMK dan SMA. “Tiga tahun gue sekolah, hampir setiap hari tawuran. Waktu itu pergi sekolah seperti taruhan nyawa,” ujar Lembah yang bersekolah di salah satu SMK di Jakarta pada awal 1990-an.
Kala itu para siswa berjalan bergerombol dengan “basis” masing-masing. Segala senjata mematikan untuk tawuran disiapkan. Perkelahian dilakukan kerap kali tanpa ada sebab musababnya. Yang penting bertarung. Siswa-siswa di Jakarta berguguran di tepi-tepi jalanan.
Menelusuri arsip Republika, pada 1993, tentara turun tangan. Adalah Pangdam Jaya Mayjen TNI AM Hendropriyono yang kala itu punya ide untuk memasukkan para siswa terlibat tawuran ke barak. Program itu kemudian beken disebut Sekolah Kodim yang bertempat di Rindam Jaya di Condet, Jakarta Timur.
Gagasan sekolah Kodim itu muncul setelah ada kecaman atas penahanan para pelajar yang berkelahi atau terjaring razia senjata tajam. Ada kekhawatiran setelah keluar dari sel, siswa itu bukan kapok, tapi malah makin beringas. Dari situ timbullah ide mendidik mereka secara khusus di Kodam Jaya.
Nuansa belajar di sekolah yang merupakan program bersama Kanwil Depdikbud DKI, Pemda DKI, Bakolak Inpres, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya itu berbeda dari sekolah lain. Gedung sekolahnya di markas ABRI, lama belajar hanya delapan hari dan tidak dipungut SPP. Pendidikan yang diberikan mencakup disiplin, olahraga, pelajaran baris berbaris dan Bela Negara.
Sejak awal rencana itu sudah memicu keberatan karena dinilai tak berbeda dengan penahanan siswa terlibat tawuran. "Silahkan saja mengkritik. Ini terbuka kok. Tujuannya juga mulia, untuk mengurangi kekacauan," kata Hendropriyono saat itu. Selama Hendropriyono menjabat, program itu terus dijalankan. Ratusan pelajar masuk barak. Kebanyakan anak-anak STM.
Apakah kemudian fenomena tawuran berhenti? Sebaliknya, perkelahian pelajar makin menjadi-jadi. Republika mencatat, pada Pameran Pembangunan Agustus 1995, tingkah laku para remaja di Jakarta itu jadi kerisauan utama. Di stan Polda Metro Jaya kala itu dipajang sebuah potret berukuran besar. Pengunjung pameran dibuat bergidik melihat potret yang dipajang di sisi pintu masuk itu.
Seorang remaja berseragam sekolah putih abu-abu tergeletak dalam posisi setengah tertelungkup. Bajunya yang putih menjadi dominan merah oleh darah dari luka-luka bacokan di sekujur tubuhnya. Tengkuk yang menjadi fokus pemotretan, terlihat luka menganga sepanjang setengah lingkaran leher dengan tulang menyembul. ''Luka bacokan celurit di tengkuk yang mematahkan tulang belakang itulah yang menewaskannya,'' kata penjaga stan.
Potret itu satu dari beberapa potret perkelahian pelajar yang dipajang polisi dalam pameran menyambut 50 Tahun Kemerdekaan Indonesia. “Kami sengaja memamerkan potret itu karena berniat menggugah para pelajar agar menghindari perkelahian antara sesama mereka sendiri. Paling tidak, mereka diingatkan akibat berkelahi yang sebenarnya tidak perlu mereka lakukan,'' kata Bambang Permantoro, kadispen Polda Metro Jaya kala itu.
Pemprov Jakarta mencatat saat itu sekitar 50 sekolah di Jakarta tergolong sebagai sekolah bermasalah, melonjak dari angka sebelumnya yang hanya delapan sekolah. Khususnya, karena sekolah-sekolah tersebut memiliki pelajar yang suka tawuran. Selama 1995, pelajar-pelajar dari 50 sekolah itu, melakukan tawuran dengan sekolah lain, minimal dua kali. Sebagian besar merupakan pelajar STM.
Data tersebut kontras dengan usaha pembinaan yang dilakukan BPKS (Badan Pembinaan Kenakalan Sekolah) di bawah naungan Pemda DKI. Badan ini telah memiliki sekitar 200 program kegiatan untuk membina anak sekolah. Baik kegiatan orang tua, guru, dan perbaikan dalam lingkungan sekolah itu sendiri. Namun disimpulkan, anak-anak bermasalah cenderung enggan mengikuti sekolah budi pekerti sebagaimana telah dilakukan Pemda DKI di kawasan Cibubur.
Guru besar psikologi Universitas Indonesia Prof Dadang Hawari saat itu menilai tindakan represif dengan mengadakan razia terhadap pelajar atau mengadakan Sekolah Kodim tak cukup. Menurutnya, akar masalah yang sesungguhnya harus dilihat dari kondisi masyarakat secara keseluruhan.
"Anak-anak remaja kita bukan anak-anak bodoh yang tidak tahu apa-apa," katanya. "Anak-anak itu juga melihat kemiskinan, kebodohan, kesenjangan sosial, dan ketidakadilan terjadi di sekitar mereka." Keadaan itu oleh Dadang dilihat sebagai penyebab anak-anak pelajar kehilangan pegangan. Tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik menjadi semakin tak jelas di mata mereka. Kita semua, kata dia, "sudah terkondisi dengan semua itu".
Datang SBY...

 1 month ago
49
1 month ago
49