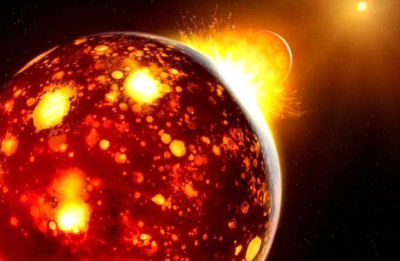Oleh : Fahmi Salim, Ketua Umum Forum Dai dan Mubaligh Azhari Indonesia
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Oleh banyak orang, perdebatan antara Salafi, Asy‘ari, dan Maturidi hari ini dianggap sebagai perdebatan akidah paling mendasar. Namun, bisa jadi problem utamanya bukan terletak pada perbedaan teologis klasik, melainkan pada cara beragama yang kehilangan adab ilmiah dan kesadaran sejarah.
Hal itu yang coba disampaikan Dr Ismail Muhammad Rif‘at, yakni “Para Pengklaim Tasawuf Tidak Berbeda dengan Para Pengklaim Salafiyah” di situs www.islamok.com dan “Menuju Pilar-Pilar Pendekatan Antar Mazhab Ahlusunnah” di situs www.aljazeera.net,
Kedua tulisan tersebut penting dibaca di tengah mengerasnya polarisasi keagamaan di ruang publik, terutama di media sosial, di mana label ahlul bid‘ah, sesat, bahkan kafir dilontarkan dengan ringan oleh mereka yang baru kemarin mengenal istilah-istilah akidah.
Klaim Kebenaran dan Ilusi Kesalehan
Tulisan pertama menyoroti dua kelompok yang secara lahir tampak berseberangan: sebagian pengklaim Salafiyah dan sebagian pengklaim tasawuf. Namun secara substansi, keduanya dinilai serupa: sama-sama membangun ilusi kesalehan. Yang satu menciptakan ilusi loyalitas kepada sunnah sambil berdamai dengan kekuasaan zalim dan menormalisasinya; yang lain menciptakan ilusi spiritualitas dengan klaim-klaim metafisik yang tidak berpijak pada wahyu.
Kritik ini tajam sekaligus relevan. Ia mengingatkan bahwa penyimpangan tidak selalu hadir dalam bentuk penolakan terhadap agama, tetapi seringkali muncul dalam rupa pembelaan agama yang kehilangan kejujuran moral. Dalam konteks ini, agama direduksi menjadi identitas ideologis, bukan jalan pembinaan akhlak dan tanggung jawab sosial.
Namun tulisan tersebut juga memberi peringatan penting: bahwa bahaya terbesar bukan pada perbedaan manhaj, melainkan pada pengkhianatan terhadap ukhuwah iman, sebagaimana ditegaskan Al-Qur’an: “Dan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain.” (QS. at-Taubah: 71)
Mengurai Akar Konflik: Kekacauan Istilah dan Sejarah
Tulisan kedua melangkah lebih sistematis dengan membedah akar konflik di internal Ahlusunnah: ketidakjelasan istilah dan amnesia sejarah. Dengan merujuk pada karya ulama klasik seperti as-Saffarini, Ibn Daqiq al-‘Id, hingga Ibn Taymiyyah, penulis menegaskan bahwa Asy‘ariyah, Maturidiyah, dan Ahlul Hadits adalah tiga mazhab dalam satu firqah, bukan tiga firqah yang saling meniadakan.
Ketiga mazhab ini adalah satu firqah, seluruhnya Ahlul Hadits, karena mereka tidak menolak hadits. Perbedaan mereka hanyalah antara tafwīḍ (menyerahkan makna hakiki kepada Allah) dan ta’wīl (penafsiran yang dibenarkan).
Mereka semua disatukan oleh istilah “Ahlut-Tanzīh” (Ahli Penyucian Allah dari keserupaan dengan makhluk), sebagaimana dikatakan as-Saffārīnī: “Mereka menetapkan nash dengan tanzīh, tanpa ta‘thīl dan tanpa tasybīh.” Istilah ini pertama kali digunakan oleh Abdul Aziz bin Yahya al-Kinani (w. sekitar 240 H), murid Imam asy-Syafi‘i.
Di sinilah letak kontribusi intelektual tulisan ini: ia membongkar mitos populer bahwa Ahlusunnah identik dengan satu ekspresi teologis tunggal. Padahal, sejarah Islam justru menunjukkan pluralitas metodologis yang diikat oleh satu tujuan utama: tanzīh, menyucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk.
Penjelasan tentang konsep tafwīḍ dan ta’wīl menunjukkan bahwa perbedaan itu berada di wilayah ijtihad linguistik dan metodologis, bukan pada substansi iman. Dengan demikian, menjadikan perbedaan ini sebagai dasar pembid‘ahan atau pengkafiran bukan hanya keliru, tetapi juga bertentangan dengan praktik salaf.
Ibn Taymiyyah dan Ironi Pewarisan Gagasan
Salah satu ironi paling mencolok yang diungkap tulisan kedua adalah bagaimana Ibn Taymiyyah—yang sering dijadikan simbol perlawanan terhadap Asy‘ariyah—justru memiliki penilaian yang jauh lebih proporsional terhadap mereka. Ia tidak mengkafirkan Asy‘ariyah, bahkan menyebut mereka sebagai kelompok mutakallimin yang paling dekat dengan Ahlusunnah.
Ironinya, sebagian pengklaim Salafiyah hari ini mewarisi retorika konflik, bukan metodologi ilmiah Ibn Taymiyyah. Mereka mengutip kritiknya, tetapi mengabaikan pujiannya; mengambil sikap kerasnya, tetapi meninggalkan keadilannya.
Di sisi lain, sebagian pengklaim Asy‘ariyah juga terjebak pada sikap serupa: menjadikan mazhab sebagai benteng identitas, bukan sebagai alat memahami wahyu. Kedua belah pihak sama-sama berisiko menjadikan mazhab sebagai ashabiyah baru.
Kontestasi Dakwah Media Sosial di Indonesia: Salafi vs Aswaja
Dalam satu dekade terakhir, lanskap dakwah Islam di Indonesia mengalami pergeseran signifikan dari mimbar masjid dan majelis taklim ke ruang digital: YouTube, Instagram, TikTok, X, dan podcast. Perpindahan medium ini tidak sekadar teknis, tetapi membawa konsekuensi epistemik dan etis yang besar. Dakwah yang sebelumnya bertumpu pada otoritas keilmuan dan sanad kini bergeser ke logika algoritma: siapa paling viral, paling tegas, dan paling provokatif.
Dalam konteks inilah kontestasi antara kelompok yang menamakan diri Salafi dan Aswaja (yang umumnya merujuk pada arus tradisionalis–Asy‘ari–Maturidi) menemukan panggung barunya. Media sosial menjadi arena perebutan makna Ahlusunnah, bukan melalui dialog ilmiah yang tenang, melainkan melalui potongan video pendek, reaction content, dan debat kusir yang sering kehilangan konteks historis dan metodologis.
Kelompok Salafi di medsos cenderung tampil dengan narasi pemurnian: Islam harus dikembalikan pada "manhaj salaf", dengan penekanan kuat pada ittiba‘ literal terhadap teks dan kecurigaan terhadap istilah-istilah teologis seperti ta’wil, kalam, dan tasawuf. Sebagian konten dakwahnya berhasil menarik generasi muda urban karena gaya penyampaian yang lugas, hitam-putih, dan menawarkan kepastian identitas di tengah kegamangan zaman. Namun, dalam banyak kasus, kesederhanaan ini dibayar mahal dengan reduksi sejarah Islam dan penyempitan makna Ahlusunnah seolah hanya identik dengan satu corak penafsiran.
Di sisi lain, dakwah Aswaja—khususnya yang berakar pada tradisi pesantren dan ormas besar—sering hadir sebagai reaksi defensif. Alih-alih menjelaskan kerangka besar Ahlusunnah secara sistematis, sebagian konten justru terjebak pada glorifikasi identitas, romantisme masa lalu, dan serangan balik personal. Tidak jarang pula label "Wahabi", "anti-NU", atau "radikal" digunakan secara serampangan, sehingga memperkeruh diskursus dan menjauhkan publik dari substansi perbedaan ilmiah yang sebenarnya.
Debat kusir pun tak terelakkan. Isu-isu klasik seperti bid‘ah, tawassul, maulid, ziarah kubur, sifat-sifat Allah, hingga definisi Ahlusunnah diperdebatkan berulang-ulang tanpa kemajuan berarti. Yang terjadi bukanlah tahqiq al-haqq (pencarian kebenaran), melainkan tahrik al-jumhur (mobilisasi emosi massa). Algoritma media sosial memperparah keadaan ini dengan memberi insentif pada konten yang memicu kemarahan dan polarisasi.
Ironisnya, kedua kubu sering mengklaim sedang membela Ahlusunnah, tetapi justru mengabaikan etos Ahlusunnah itu sendiri: adab dalam ikhtilaf, pengakuan terhadap khilaf mu‘tabar, dan kesadaran bahwa kebenaran metodologis tidak selalu identik dengan kemenangan retorika. Padahal, sebagaimana ditunjukkan oleh sejarah panjang Islam—termasuk dalam dua tulisan yang dianalisis—Ahlusunnah sejak awal adalah payung besar yang menaungi perbedaan, bukan pagar sempit yang memonopoli surga.
Jika kontestasi dakwah digital ini terus dibiarkan tanpa koreksi etis dan intelektual, umat hanya akan mewarisi kelelahan polemik, bukan kedalaman iman. Tantangannya bagi para dai, intelektual, dan pengelola ormas Islam di Indonesia hari ini bukan sekadar memenangkan perdebatan, melainkan mengembalikan dakwah pada fungsinya: membimbing, mencerahkan, dan mempersatukan umat di tengah keberagaman mazhab yang sah dan berakar dalam tradisi Islam itu sendiri.
Jalan Tengah yang Hilang
Dua tulisan Dr Ismail Rif’at, ulama Al-Azhar yang berdakwah di Jerman, jika dibaca bersama, sebenarnya sedang menawarkan satu pesan besar: Islam Ahlusunnah adalah jalan tengah yang kini justru ditinggalkan oleh para pengklaimnya. Jalan tengah itu bukan sikap abu-abu tanpa prinsip, melainkan keberanian untuk membedakan antara wilayah ushul dan furu‘, antara yang qath‘i dan yang ijtihadi.
Upaya taqrīb (pendekatan) antar mazhab Ahlusunnah bukan proyek kompromi akidah, melainkan proyek pemulihan adab berbeda pendapat. Sebagaimana umat Islam menerima perbedaan qira’at Al-Qur’an tanpa saling menyesatkan, demikian pula seharusnya mereka menyikapi perbedaan teologis internal Ahlusunnah.
Darii Polarisasi ke Tanggung Jawab Ilmiah
Krisis keberagamaan hari ini bukanlah krisis dalil, melainkan krisis kedewasaan. Kita hidup di zaman di mana akses terhadap kitab-kitab klasik begitu mudah, tetapi kesabaran membaca dan kerendahan hati untuk memahami semakin langka.
Dua tulisan Dr Ismail Muhammad Rif‘at patut dibaca sebagai cermin kritik diri bagi semua pihak. Bahwa membela sunnah tanpa adab adalah kesia-siaan; dan membela mazhab tanpa kejujuran sejarah adalah bentuk lain dari penyimpangan.
Jika Ahlusunnah ingin tetap menjadi arus utama Islam yang rahmatan lil ‘alamin, maka tugas terpentingnya hari ini bukan memperbanyak musuh internal, melainkan menghidupkan kembali etika ilmiah, keadilan dalam menilai, dan ukhuwah yang berakar pada iman—bukan pada slogan.
Jakarta, 21 Januari 2026

 1 month ago
77
1 month ago
77