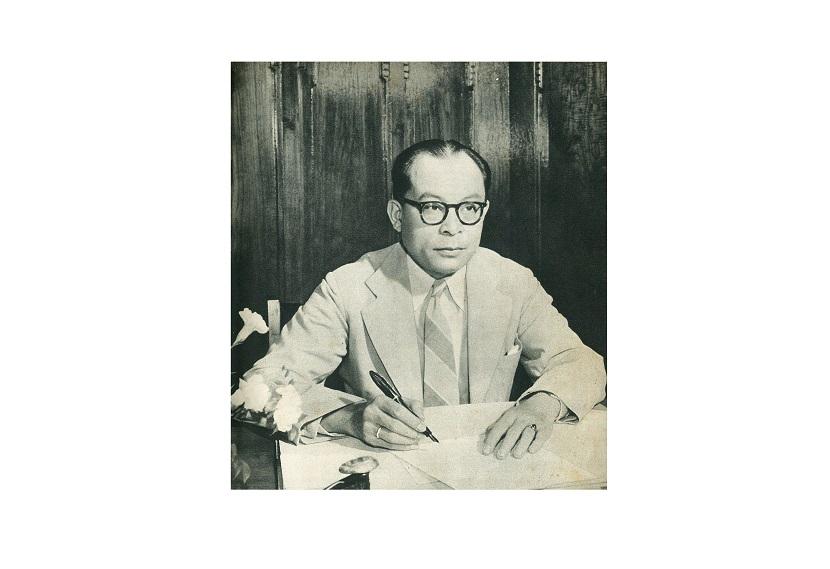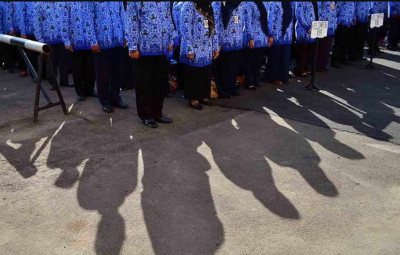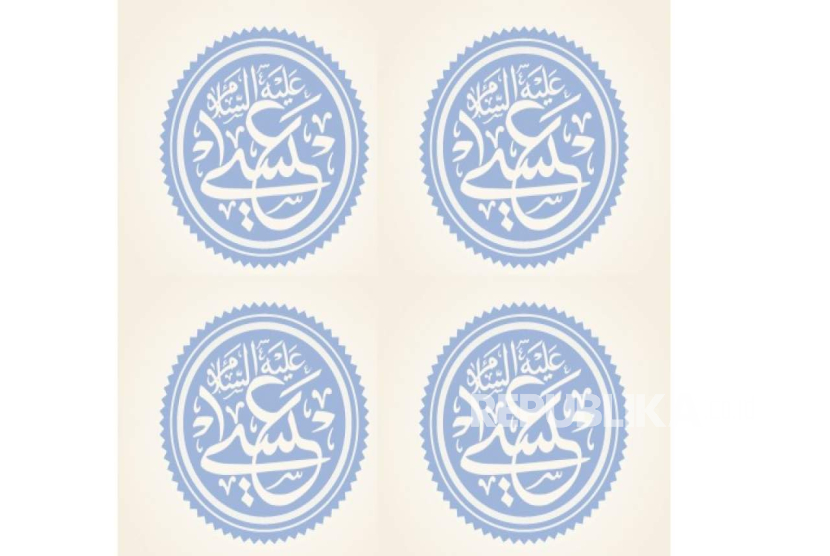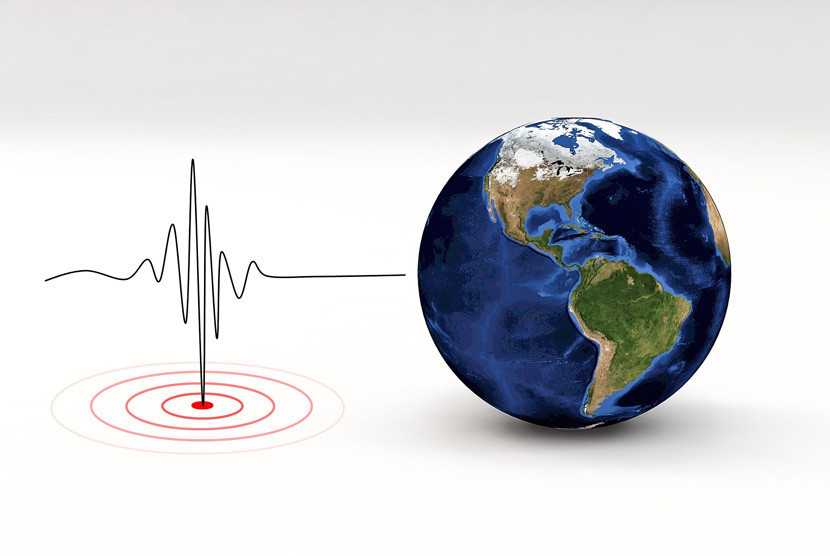 Ilustrasi gempa. Foto : pixabay
Ilustrasi gempa. Foto : pixabay
Oleh Yenny Narny
Sekitar satu setangah bulan lalu, Asia Tenggara diguncang kabar duka dari Myanmar. Gempa bermagnitudo 7,7 yang berpusat dekat Kota Sagaing merenggut lebih dari 3.700 nyawa, melukai ribuan orang, dan menghancurkan lebih dari 10 ribu bangunan. Di balik angka-angka tragis itu, tersingkap satu kenyataan pahit: kita masih sangat rentan. Lemahnya infrastruktur, minimnya kesiapsiagaan, dan yang paling mengkhawatirkan—pengabaian terhadap pengetahuan lokal yang sebetulnya telah lama hidup berdampingan dengan masyarakat.
Tragedi ini seakan menggaungkan kembali pelajaran berharga dari dua dekade silam di Indonesia. Tahun 2004, gelombang tsunami menghantam Aceh dan menewaskan lebih dari 230 ribu orang. Namun, ada satu kisah yang berbeda di Pulau Simeulue. Nyaris seluruh penduduknya selamat. Bukan karena teknologi canggih atau peringatan dini dari pusat. Mereka hanya berpegang pada satu kata: Smong. Sebuah warisan lisan yang diturunkan lewat cerita, nyanyian, dan nasihat orang tua. Saat gempa datang dan laut surut, mereka tahu harus segera lari ke tempat tinggi. Bukan sains modern yang menyelamatkan mereka, melainkan ingatan kolektif tentang kematian sis-sia sebanyak 1.800 jiwa di tahun 1907 (M Zuhairi, 2024), yang kemudian hidup dalam budaya mereka.
Scroll untuk membaca
Scroll untuk membaca
Smong bukanlah hasil riset di laboratorium, tapi refleksi dari pengalaman panjang menghadapi bencana. Ia sederhana, kontekstual, dan terinternalisasi dalam budaya nafi-nafi dan nandong yang merupakan bagian dari kehidupan mereka. Inilah bukti bahwa kearifan lokal bukan sisa masa lalu, melainkan sistem pengetahuan yang masih sangat relevan dan fungsional hari ini.
Dan Smong bukan satu-satunya. Dari berbagai belahan dunia, kita melihat pola serupa. Di Turpan, Tiongkok, masyarakat sejak ribuan tahun lalu membangun sistem irigasi bawah tanah bernama Karez (U.cui, et.al, 2012) untuk mengalirkan air dari pegunungan ke gurun. Di Kashmir, teknik bangunan tradisional Dhajji Dewari (Naomaan R, at.all, 2023) terbukti lebih tahan gempa dibanding bangunan modern. Bahkan di Indonesia sendiri, kita punya Repong Damar di Lampung (Ahmad T, et.all, 2023), , rumah panggung, hingga sistem tafsir alam seperti Ta’bir Gempa (Pegi A, et.all, 2020) dan Nandong Smong (M Zuhairi, 2024).
Namun sayangnya, semua ini kerap hanya hadir sebagai “hiasan” dalam kebijakan mitigasi bencana. Sekadar simbol budaya tanpa diberi ruang untuk berkontribusi secara nyata. Istilahnya, tokenisasi. Kearifan lokal hanya dipamerkan, bukan dijadikan landasan.
Hal ini mencerminkan ketimpangan cara pandang. Seolah hanya pengetahuan yang bisa dihitung dan disajikan dalam format proyek yang layak dianggap ilmiah. Padahal, pengetahuan lokal lahir dari interaksi langsung antara manusia dan lingkungannya—lebih dari sekadar teori, tapi praktik yang telah teruji waktu.
Kita butuh perubahan paradigma. Sudah saatnya pendekatan top-down digantikan oleh kolaborasi sejajar antara ilmuwan, birokrat, dan masyarakat lokal. Prinsip ko-produksi pengetahuan—di mana semua pihak duduk setara dalam merancang mitigasi—harus jadi dasar kebijakan. Kearifan lokal tak lagi ditempatkan sebagai pelengkap, melainkan sebagai fondasi.
Caranya? Mulailah dari pelembagaan. Bentuk unit khusus di BNPB atau BPBD yang fokus pada pengetahuan adat. Susun indikator mitigasi yang sesuai dengan konteks budaya. Salurkan dana desa atau hibah untuk mendukung praktik komunitas. Pendidikan pun harus menjadi medium penyebaran: lewat kurikulum sekolah, media populer seperti film dan komik, hingga platform digital yang digemari anak muda.
Teknologi pun bisa bersinergi. Bayangkan aplikasi peringatan dini yang berbicara dalam bahasa daerah, menggunakan simbol lokal, bahkan terintegrasi dengan pengetahuan . Alih-alih menggantikan, teknologi harus melengkapi. Namun, semua itu tak akan cukup tanpa satu hal paling mendasar: pengakuan atas hak-hak masyarakat adat terhadap tanah dan ruang hidup mereka. Sebab, ketangguhan bukan sekadar urusan teknis. Ia terkait erat dengan identitas, keyakinan, dan relasi spiritual manusia dengan alamnya.
Kearifan lokal bukan tandingan modernitas. Ia bagian dari peradaban. Ia tidak anti-ilmu, hanya menawarkan perspektif lain dalam memahami dunia. Dari Smong hingga Karez, dari Dhajji Dewari hingga Repong Damar, semuanya mengingatkan kita: ketangguhan sejati tumbuh dari akar, dari hubungan yang hidup antara manusia dan alam.
Kini saatnya negara mulai pengetahuan yang tumbuh dari bumi tempat kita berpijak (kearifan lokal) sebagai mitra sejajar sebab di sanalah, sebenarnya, ketangguhan kita berakar.(*)
Penulis adalah Sekretaris Prod Magister Bencana Sekolah Pasca Sarjana Unand dan Profesor di bidag Sejarah Sosial.

 1 month ago
64
1 month ago
64