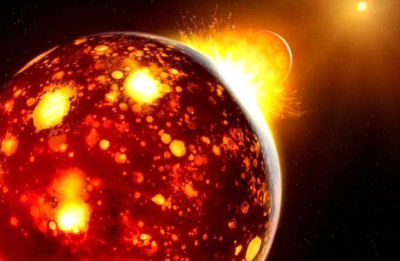REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pusat Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia Fakultas Hukum UGM (PANDEKHA FH UGM) membuka tahun 2026 dengan diskusi tahunan Bulaksumur Legal Outlook 2026. Forum ini membahas bagaimana refleksi hukum sepanjang 2025 dan proyeksi isu kritis di tahun ini. Salah satu yang disoroti adalah tantangan demokrasi elektoral pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024.
Ketua Departemen Hukum Tata Negara UGM, Prof Zainal Arifin Mochtar yang mengawali forum menyebut putusan MK tersebut memutuskan pemisahan pemilu nasional dan lokal, yakni pemilihan Presiden, DPR, dan DPD dilakukan secara terpisah dari pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, serta DPRD. Tujuan utamanya, seharusnya adalah untuk memperbaiki demokrasi agar dominasi partai politik tertentu tidak terjadi dan isu lokal tetap hidup.
"Pemilu lokal harus terjadi dua sampai dua setengah tahun setelah pemilu nasional. Ini memberi waktu bagi masyarakat untuk benar-benar menilai kandidat dan menyeimbangkan kekuasaan partai besar," katanya dalam forum Bulaksumur Legal Outlook 2026, Senin (05/1/2026).
Namun, sejak putusan itu keluar, banyak kalangan politisi yang justru mencoba menggeser arah implementasinya. Beberapa usulan mengusulkan pemilihan kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD, bahkan ada indikasi wacana serupa untuk Presiden dan Wakil Presiden dipilih melalui MPR.
"Kalau Pilkada dipilih DPRD, maka pemisahan antara pemilu lokal dan nasional menjadi tidak relevan. Kedaulatan rakyat dipertaruhkan di sini," ucapnya.
Pria yang akrab disapa Uceng ini mencatat ada tiga skenario berbahaya yang berpotensi terjadi pada 2026, pertama, putusan MK akan diterabas dan Pilkada dipilih DPRD seperti praktik lama. Kemudian ia juga membayangkan apabila DPRD tetap dipilih, tapi MK didomestikasi agar tidak independen. Ketiga, skenario terburuk, Pilkada DPRD dipaksakan, dan pemilihan Presiden-Wapres pun masuk jalur tidak langsung.
Prof Uceng menyebut, ide ini tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerindra, yang ingin mengembalikan konstelasi UUD sebelum amandemen. Ia menekankan meskipun pemilihan kepala daerah oleh DPRD secara hukum tidak haram, arah sejarah dan konstitusi jelas menekankan prinsip pemilihan langsung. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen kedua menetapkan kepala daerah dipilih secara demokratis, yang secara konsisten diterjemahkan mengikuti model Pilpres hasil amandemen ketiga (2001).
"Sesuai sejarah, kata ‘dipilih secara demokratis’ disepakati mengikuti Pilpres, yaitu langsung oleh rakyat. Mengembalikan Pilkada ke DPRD berarti kembali ke praktik lama Orde Baru, membatasi kompetisi dan merugikan partai-partai kecil," ucapnya.
Prof Uceng kemudian mengungkapkan kekhawatirannya terhadap munculnya ide untuk membunuh pilkada langsung dan menggantikannya dengan pemilihan oleh DPRD.
"Gara-gara putusan MK 135 ini, lahirlah ide untuk membuat Pilkada dipilih DPRD," katanya.
Ia menambahkan, jika pilkada dipilih DPRD, maka tidak relevan untuk menghukum partai yang gagal menjalankan pemerintahan. Pasalnya yang berperan dalam pemilihan adalah DPRD, bukan rakyat.
"Ini bisa melemahkan kontrol politik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah," ujarnya.
Menurutnya, isu pilkada bukan hanya persoalan hukum atau teknis, tetapi menyangkut hak politik rakyat dan kualitas demokrasi di Indonesia. Pemisahan pemilu nasional dan lokal, jika dijalankan dengan benar, memberikan kontrol lebih besar bagi rakyat. Tetapi justru sebaliknya, jika pilkada dipilih DPRD, kontrol ini bisa hilang, dan demokrasi elektoral bisa mengalami kemunduran serius.
"Ini bukan soal legalitas semata, tapi soal masa depan demokrasi kita. Pilihan rakyat harus tetap menjadi pusat, bukan keputusan partai atau lembaga tertentu. Kalau ini diabaikan, bukan hanya Pilkada yang hilang, tetapi seluruh semangat reformasi," ucapnya.
Diskusi juga menyoroti risiko politik balik arah ini bagi demokrasi. Ketua Pandekha FH UGM, Yance Arizona, mengatakan jika Pilkada dipilih DPRD, partai-partai besar berpotensi mengendalikan hasil, sedangkan partai menengah atau kecil akan kehilangan peluang bersaing secara adil. Ia menyebutnya sebagai 'sinyal dominasi politik dan represi demokrasi kembali ke imajinasi Orde Baru'.
“Kalau sistem ini terjadi, pemerintah pusat bisa mengkondisikan siapa yang jadi kepala daerah. Tidak ada pilihan bagi rakyat. Itu bukan pemilihan demokratis," kata Yance.
Menurutnya, skema Pilkada DPRD menyerupai lotre politik. Partai-partai menengah seperti PKB mungkin setuju karena mengira bisa mendapat keuntungan, tetapi faktanya tidak pasti. Keputusan final akan sangat dipengaruhi elit pusat, terutama figur politik yang dominan. Yance juga menyoroti posisi putusan MK yang setara dengan undang-undang dan menekankan pentingnya MK memberikan arahan jelas agar putusannya bisa dijalankan sesuai maksud demokratisnya.
Tanpa arahan yang jelas, pelaksanaan putusan rawan diabaikan, seperti pengalaman putusan MK terkait undang-undang Polri.
"Saya mengatakan 2026 ini saya sedikit khawatir akan ada upaya untuk membalik roda sejarah. Balik ke praktik-praktik yang terjadi di zaman Orde Baru. Praktik-praktik, Kalaupun ada proses legislasinya dia meaningless participation," ucapnya.
"Saya juga bertanya mengapa doa menjadi sulit terkabulkan di negeri ini belakangan? Mengapa doa menjadi sulit, Walaupun dilafalkan oleh ratusan orang, dimintakan oleh jutaan orang, seperti untuk segera menjadikan status bencana nasional, toh pemerintah punya pikiran sendiri, selalu begitu. Jadi, silahkan berdoa, Tapi rasa-rasanya pemerintah akan punya pikiran sendiri. Dan, satu harapan terakhir saya tentu saja adalah, kemauan untuk teman-teman, menaikkan kembali gairah perlawanan, sekurang-kurangnya Garuda Biru, Geruda apapun namanya. Perlawanan itu yang harus diagregasi, karena, bahaya dari ini semua adalah, merampok daulat rakyat," pesannya.
Senada, Herlambang P. Wiratraman dari Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial menyoroti lima isu utama yang memprihatinkan di 2025. Pertama, pelemahan kebebasan sipil terlihat dari kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan warga sipil, termasuk kasus terhadap Greenpeace dan sejumlah influencer yang mendapat tekanan.
"Kejadian ini bukan baru, tetapi terus berulang tanpa pertanggungjawaban. Ini menunjukkan lemahnya perlindungan kebebasan sipil," kata Herlambang.
Kedua, ia menekankan penguatan militerisme yang melemahkan supremasi sipil. Revisi undang-undang TNI dan keterlibatan militer dalam proyek politik dan publik menjadi indikasi meningkatnya pengaruh militer di berbagai sektor. Ketiga, Herlambang mengingatkan dampak bencana kebijakan di Aceh dan Sumatra yang menimbulkan 1.117 korban jiwa dan 242 ribu pengungsi.
Respons pemerintah yang lamban dan tidak menetapkan status darurat bencana nasional, dinilainya, berdampak serius pada hak hidup warga.
Keempat, serangan terhadap kebebasan pers meningkat, termasuk intimidasi dan perampasan alat kerja jurnalis oleh anggota TNI. Dan poin terakhir yang ia soroti adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dianggap melanggar HAM. Anggaran program ini meningkat dari Rp 71 triliun menjadi Rp 335 triliun pada 2026, sementara kualitas layanan publik dan bantuan untuk korban bencana sosial-ekologis tetap terabaikan.
"Sedari awal kita membuat catatan bahwa MBG ini jelas melanggar hak asasi manusia karena telah menurunkan kualitas derajat layanan publik, terutama sektor dasar baik pendidikan, kesehatan, ataupun layanan publik yang lain. Bahkan penganggarannya pun tidak dilakukan secara proses yang konstitusional dan mengambil anggaran-anggaran untuk kemudian dialihkan untuk MBG," kata Herlambang.
Bahas Perizinan
Selain itu, forum ini juga menyoroti isu kelembagaan dan hukum lain yang tidak menyentuh akar persoalan. Ketua Departemen Hukum Administrasi Negara UGM, Richo Andi Wibowo, menyoroti perizinan dan pengelolaan ruang publik. Menurutnya, kebijakan saat ini lebih bersifat reaktif, menangani masalah setelah terjadi, daripada mencegah sejak awal.
"Perizinan harus menjadi logika pengendalian, bukan memproduksi bencana. Pemerintah perlu memperbaiki regulasi dan komitmen, memastikan masyarakat menjadi subjek, bukan objek," kata dia.
Ia juga menilai Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang dibentuk pemerintah hanya menangani masalah secara permukaan tanpa menyentuh akar persoalan. Salah satu masalah utama adalah perizinan, yang selama ini kerap bermasalah, mulai dari praktik pungli, tumpang tindih aturan, regulasi yang berlebihan, hingga konflik kewenangan antara pemerintah daerah dan pusat.
Sejak 2016, pemerintah mencoba melakukan reformasi melalui pembentukan UU Cipta Kerja. Perizinan mulai dikelola secara terpusat melalui OSS (Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik), yang memungkinkan izin diberikan berdasarkan data digital tanpa verifikasi lapangan. Akibatnya, perizinan lingkungan dan persetujuan masyarakat cenderung dilonggarkan, sementara masyarakat terdampak kesulitan mengakses OSS karena tidak dianggap sebagai pengguna.
"Yang saya lihat, sudah terjadi baru (pemerintah) action. Setelah semuanya selesai, kejadian hari ini (bencana di Sumatera, Aceh) memperlihatkan bahwa pemerintah mengontrol perizinan setelah adanya masalah. Perizinan adalah logika pengendalian, harusnya sebelum adanya masalah. Perlu diingat, perizinan jangan sampai memproduksi bencana, jangan sampai menciderai lingkungan sosial. Karena itu pemerintah perlu memperbaiki cara berpikir dan perlu memperbaiki regulasi dan komitmen mereka," ujarnya.
Sementara itu, Totok Dwi Diantoro dari Pusat Kajian Anti Korupsi UGM juga menyampaikan paparannya terkait stagnasi agenda pemberantasan korupsi di negeri ini. Menururtnya, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pada 2025 masih stagnan, melanjutkan tren beberapa tahun terakhir. Publik berharap ada tindakan tegas, tetapi kenyataannya sering bertemu kebijakan yang ambigu dan retorika belaka.
Meski masih ada operasi tangkap tangan, persidangan, dan putusan pengadilan, upaya pemberantasan korupsi minim terobosan dan tidak signifikan.
"Terlihat jelas bahwa upaya pemberantasan korupsi kehilangan daya dorong dan arah strategis," katanya.
Kelemahan ini terlihat dari kasus-kasus yang melibatkan elit atau pihak berpengaruh, misalnya korupsi pembangunan jalan di Sumatera Utara yang menyeret Gubernur Bobby Nasution. "Tokoh-tokoh berpengaruh jarang diperiksa atau diusut secara serius," ungkapnya.
Harapannya dengan adanya diskusi Bulaksumur Legal Outlook 2026, mampu mengingatkan bahwa dinamika Pilkada dan penguatan demokrasi harus tetap dipantau publik agar kedaulatan rakyat tidak hilang di tengah kepentingan politik elit.

 1 month ago
79
1 month ago
79