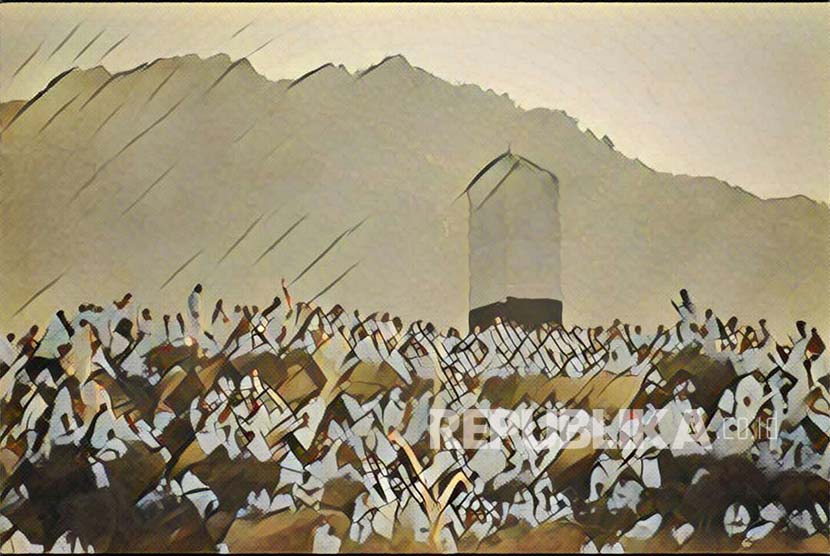Gili Argenti
Gili Argenti
Sejarah | 2025-09-21 15:55:03

Sesungguhnya keterlibatan pelajar di dunia pergerakan bukan sesuatu yang baru, di dalam sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia, peran mereka hampir sama dengan para seniornya, yaitu mahasiswa, sebagai lokomotif perubahan di negeri ini. Jadi ketika terdapat polemik terkait aktivisme di kalangan pelajar, seharusnya hal itu tidak terjadi, karena generasi pendahulu telah mencatatkan warisan keterlibatan pelajar di dalam dunia pergerakan.
Bahkan bapak pendiri bangsa mengalami kesadaran politik ketika berstatus sebagai pelajar, diantaranya adalah Soekarno, ketika mengenyam pendidikan di tingkat HBS (Hogere Burgerschool) di Kota Surabaya, HBS merupakan sekolah menengah umum setara dengan SMA saat ini. Ketika itu Soekarno tinggal di Rumah Kosan milik Haji Oemar Said Tjokroaminoto, tokoh Sarekat Islam (SI) yang sangat berpengaruh.
Di Rumah Kosan Tjokroaminoto, Soekarno berkenalan dengan berbagai pemikiran dan ideologi politik, dari spektrum kiri sampai kanan, melalui perpustakaan pribadi milik Tjokroaminoto, Soekarno bersama kawan-kawan satu kosan, larut di dalam berbagai literatur lengkap, hasil bacaan dan diskusi di antara anak-anak kosan ini, akhirnya membentuk kesadaran politik dan semangat kebangsaan (Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia, 2010).
Kemudian Sutan Sjahrir ternyata memiliki pengalaman sama dengan Soekarno, tumbuh kesadaran politiknya ketika berstatus sebagai pelajar, tepatnya ketika bersekolah di AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung, AMS adalah jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas (SMA) dalam sistem pendidikan kolonial Belanda.
Ketika berstatus sebagai pelajar ini, Sjahrir mendengarkan pidato politik Dr. Tjipto Manginkusumo di alun-alun kota Bandung, dari situlah dia mengalami transformasi di dalam dirinya, Sjahrir terpukau semangat kebangsaan, akhirnya memilih terjun sebagai aktivis pergerakan politik, mendirikan perkumpulan “Jong Indonesie” dan majalah pergerakan, dampaknya Sjahrir menjadi salah satu pelajar diawasi mata-mata Belanda (Sjahrir Peran Besar Bung Kecil, Majalah Tempo, 2010).
Begitu juga dengan sosok Mohammad Natsir, ketika beliau bersekolah di AMS (Algemene Middelbare School) di Bandung, kesadaran politik muncul selain dari hasil bahan bacaan yang di peroleh, juga proses berinteraksi antara dirinya dengan para cendikiawan dan aktivis Islam, seperti Agus Salim dan Prawoto Mangkusasmito.
Ketika berstatus sebagai pelajar AMS, Natsir sudah aktif di dalam berbagai organisasi pergerakan Islam, dia menjadi aktivis Jong Islamiten Bond (JIB), Muhammadiyah, dan Partai Syarikat Islam (PSI). Bahkan di usia masih sangat muda itu, Natsir terlibat polemik tentang pemikiran Islam, ketika dia mendengar langsung pidato seorang pendeta Kristen bernama Ds. Christoffels, Natsir tidak sependapat dengan isi pidatonya itu yang di nilainya menyudutkan Islam. Besok harinya isi pidato itu di muat di halaman surat kabar AID (Algemeen Indish Dagblad), kemudian Natsir menjawab isi pidato sang pendeta, dengan menulis artikel yang mengkritisi tulisan Ds. Christoffels di surat kabar yang sama (Husaini dan Setiawan, 2020).
Dari ketiga narasi bapak bangsa itu, kita memperoleh informasi penting, bahwa kesadaran kebangsaan ketiganya sudah muncul ketika berstatus pelajar, artinya mereka di usia sangat muda sudah memahami adanya ketidakadilan serta diskriminasi, dampak dari kolonialisme dan imperialisme dunia barat.
Pemerintah Orde Baru
Pasca kemerdekaan Indonesia peran spektakuler pelajar di dalam transformasi sosial-politik, terjadi ketika bersama mahasiswa di tahun 1966, berhasil menggulingkan pemerintahan Orde Lama. Para pelajar membentuk organisasi pergerakan sosial bernama KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar-Pelajar Indonesia), wadah bagi para pelajar tingkat SMA untuk melakukan aksi demonstrasi, long march, dan aksi protes di Jakarta ketika itu.
Kejatuhan pemerintahan Orde Lama, serta berdirinya pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pada awalnya banyak diharapkan generasi muda (pelajar dan mahasiswa), mampu menciptakan pemerintahan baru yang bersih dan berkeadilan, serta tersedianya ruang publik yang luas, dimana berbagai pendapat, kritikan, dan masukan dari masyarakat, mendapatkan tempat penyaluran semestinya. Ruang publik itu diharapkan terbebas dari dominasi, intervensi, dan tekanan, sehingga masyarakat dapat melakukan fungsi sebagai kekuatan civil society, pengawasan dan kontrol yang kuat pada pemerintah.
Harapan generasi muda itu ternyata berbanding terbalik, disebabkan kebijakan di tempuh pemerintah Orde Baru, tidak menjadikan politik sebagai panglima, tetapi menjadikan sektor pembangunan-ekonomi sebagai kiblat utama rezim penguasa, dengan menekan munculnya konflik politik, yang dianggap dapat mengganggu stabilitas pembangunan.
Di bawah ini terdapat beberapa kebijakan Orde Baru, bentuk dari pengendalian konflik politik, serta untuk memperkuat dominasi kekuasaan.
Pertama, kebijakan fusi partai politik, beberapa partai politik warisan demokrasi terpimpin, dan partai baru dipaksa meleburkan diri menjadi dua partai politik. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merupakan fusi dari Parmusi, NU, PSII dan Perti. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hasil dari gabungan Partai Murba, PNI, Partai Katolik, IPKI, dan Parkindo.
Kedua, Orde Baru menuntut para birokrat untuk loyal kepada pemerintah, mengkondisikan kesetiaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada partai penguasa dan melarang birokrat aktif di partai politik lain. Ketiga, kebijakan massa mengambang, Orde Baru mendorong rakyat menjadi pasif secara politik, tidak terlibat organisasi politik kecuali saat pemilu, serta melarang aktivitas partai sampai ke tingkat kecamatan serta desa, kecuali partai penguasa.
Keempat, menetapkan asas tunggal Pancasila bagi partai politik dan organisasi masyarakat (Ormas) melalui Undang-Undang Nomor 8/1985, mewajibkan semua organisasi kemasyarakatan, partai politik, dan lembaga di Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berpolitik.
Perlawanan Pelajar Islam Indonesia (PII).
Pelajar Islam Indonesia (PII) merupakan organisasi pelajar Islam se-Indonesia berdiri pada tanggal 4 Mei 1947 di Yogyakarta, PII menjadi organisasi sangat kritis pada pemerintah Presiden Soekarno, terutama menolak konsep Nasakom (Nasional, Agama, dan Komunis), bahkan ketika pembentukan KAPPI (Kesatuan Aksi Pelajar-Pelajar Indonesia) untuk mengkritik kebijakan Orde Lama, PII memiliki peran mempelopori pendirian kesatuan aksi itu (Hanan, 2006).
Kekuatan PII terletak pada sistem pengkaderan, kegiatan pengkaderan ini biasanya dilakukan di pesantren, madrasah, dan sekolah umum, bahkan dibeberapa pesantren PII menjadi organisasi resmi para santri, sistem kaderisasi PII berupa kursus politik, manajemen organisasi, dan latihan kepemimpinan, sedangkan di sekolah-sekolah umum berupa pemberian kursus agama Islam, materi keislaman diberikan melalui ceramah, kegiatan ini dilakukan ketika libur sekolah, sebelum masuk tahun ajaran baru.
Ketika Orde Baru membuat Undang-Undang Nomor 8/1985 tentang keormasan, menuai polemik ditengah-tengah masyarakat, terutama di pasal dua yang berbunyi “semua organisasi kemasyarakatan harus berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”.
Pelajar Islam Indonesia (PII) bereaksi keras, bagi mereka undang-undang ini memiliki agenda terselubung, yaitu ingin mengatur serta mengendalikan kehidupan organisasi masyarakat agar sesuai dengan arah kebijakan politik pemerintah, PII menolak setiap aturan yang mengeliminasi Islam dari Anggaran Dasar perangkat organisasi, karena membatasi hak-hak asasi manusia, terutama di dalam mengembangkan nilai-nilai keislaman, PII tidak anti pada Pancasila sebab semua sila di dalamnya tidak bertentangan dengan Islam, bagi PII dengan adanya undang-undang itu berdampak matinya kemandirian organisasi masyarakat, ketika berhadap-hadapan dengan penguasa (Hanan, 2006).
Bentuk perlawanan dilakukan PII diantaranya, materi-materi pengkaderan dilakukan dengan menyisipkan materi-materi bermuatan ideologis, tentang ketidaksetujuan atas Undang-Undang Nomor 8/1985. Puncak perlawanan dilakukan PII, tidak mengeluarkan pernyataan menyesuaikan diri dengan Undang-Undang itu, hal ini merupakan bentuk perlawanan paling berani para pelajar Islam, pada saat Orde Baru sedang berada di puncak kekuasaan (Hanan, 2006).
Pelarangan Jilbab
Pada tahun 1984, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, mengeluarkan edaran tentang peraturan seragam sekolah, berdampak pelarangan jilbab yang digunakan para pelajar, karena di dalam aturan itu belum mengakomodir jilbab sebagai salah satu seragam resmi, bisa dipakai dilingkungan sekolah-sekolah negeri (Syabirin, 2014).
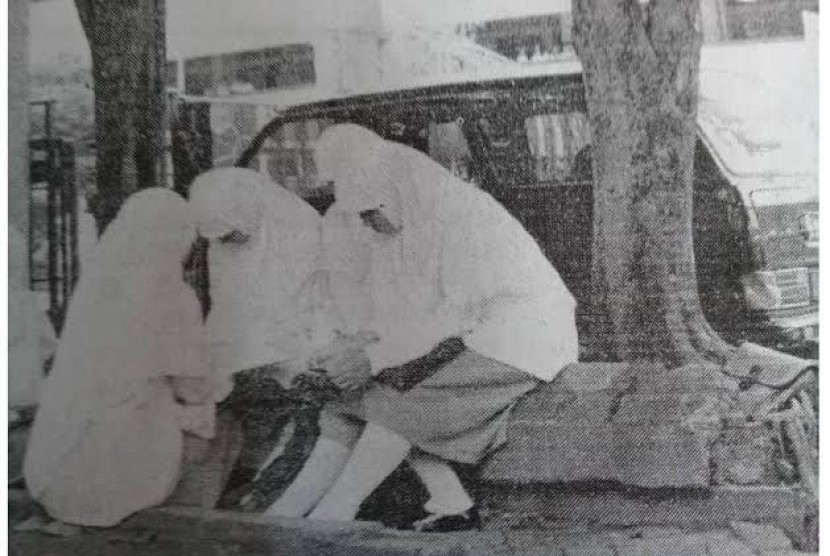
Kesadaran pelajar Islam di Indonesia pada awal tahun 1980-an, tentang kewajiban menggunakan jilbab bagi para muslimah, tidak bisa dilepaskan dari keberhasilan kaderisasi dilakukan PII ke berbagai sekolah-sekolah umum.
Para siswi ini umumnya memakai jilbab setelah mereka mengikuti pelatihan keislaman PII, para instruktur pelatihan itu kebanyakan dari kalangan mahasiswa dari kampus-kampus negeri seperti UI, IKIP Jakarta, dan IAIN Jakarta. Para mahasiswa itu banyak menggunakan referensi keislaman karya para pemikir Islam kontemporer seperti Hasan al-Banna, Abu Ala Al-Maududi, dan Sayyid Qutb. Sebetulnya tidak ada materi khusus tentang jilbab di dalam pelatihan itu, tetapi motivasi berjilbab disisipkan di dalam materi akhlak, para instruktur menunjukkan dalil wajibnya jilbab di dalam Al-Quran (Alatas dan Desliyanti, 2001).
Akibat dari pelarangan penggunaan jilbab di sekolah-sekolah negeri, mengakibatkan para siswi terpaksa masuk sekolah melalui jendela, karena pintu di kunci oleh pihak sekolah, mereka tidak boleh mengikuti pelajaran olah raga. Para siswi berjilbab di absen sebagai murid tidak hadir di kelas, mereka boleh mengikuti pelajaran, tetapi semua yang mereka ikuti baik praktikum, pekerjaan rumah, termasuk ulangan tidak mendapatkan nilai (Alatas dan Desliyanti, 2001).
Bahkan dibeberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Bogor, para siswi berjilbab itu akhirnya dipulangkan ke rumah orang tua mereka, serta disarankan pindah ke sekolah yang dikelola oleh ormas Islam, dampak kebijakan itu menuai protes tidak saja dari pihak orang tua siswi yang berjilbab, tetapi masyarakat umum.
Pihak orang tua dan siswi berjilbab menempuh jalur hukum menggugat diskriminasi itu, di kota Bogor para siswi berjilbab, akhirnya diperbolehkan menggunakan jilbab di lingkungan sekolah negeri, sedangkan di Jakarta mereka kalah di pengadilan, kemudian menempuh banding, menariknya banding mereka dikabulkan pada tahun 1995, ketika para siswi berjilbab itu sudah pindah dan menamatkan pendidikan SMA, serta sudah masuk ke perguruan tinggi, sejak saat itu penggunaan jilbab di sekolah negeri diakomodasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Alatas dan Desliyanti, 2001).
Penutup
Kebijakan politik yang bersifat represif terhadap kebebasan beragama dan berorganisasi justru memunculkan perlawanan moral dari masyarakat. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa nilai kebebasan berkeyakinan dan hak berekspresi tidak dapat sepenuhnya dibungkam oleh kekuasaan, serta menjadi bagian penting dalam sejarah demokratisasi Indonesia.
Gili Argenti, Dosen FISIP Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA).
Referensi Artikel
1. Alatas, Alwi dan Desliyanti, Fifrida. 2001. Revolusi Jilbab : Kasus Pelarangan Jilbab di SMA Negeri Se-Jabotabek 1982-1991 (Jakarta, Al-I’tishom).
2. Hanan, Djayadi. 2006. Gerakan Pelajar Islam Di Bawah Bayang-Bayang Negara : Studi Kasus Pelajar Islam Indonesia Tahun 1980-1997 (Yogyakarta, UII Press).
3. Husaini, Adian dan Bambang Galih Setiawan. 2020. Pemikiran Perjuangan M. Natsir dan Hamka dalam Pendidikan (Jakarta, Gema Insani).
4. Seri Buku Tempo : Bapak Bangsa. 2010. Sjahrir Peran Besar Bung Kecil (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia).
5. Seri Buku Tempo : Bapak Bangsa. 2010. Sukarno Paradoks Revolusi Indonesia (Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia).
6. Syabirin, Tabrani. 2014. Menjinakkan Islam Strategi Politik Orde Baru (Jakarta, Teras).
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 1 month ago
46
1 month ago
46