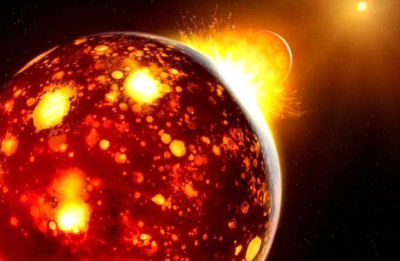Oleh : Agus Supangat, Ilmuwan senior di Pusat Perubahan Iklim, ITB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasi militer Amerika Serikat (AS) pada 3 Januari 2026 yang menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya di Caracas mengguncang peta geopolitik global. Aksi sepihak ini tidak hanya menimbulkan kecaman luas di Amerika Latin, tetapi juga menandai erosi serius Doktrin Monroe—doktrin klasik yang selama dua abad menjadi fondasi supremasi AS di Belahan Barat.
Ironisnya, langkah yang diklaim sebagai penegasan kepemimpinan global AS justru berpotensi membuka ruang manuver strategis bagi China di kawasan Asia-Pasifik, termasuk Asia Tenggara. Di tengah dunia yang kian multipolar, tindakan unilateral semacam ini mengirim sinyal ambigu: di satu sisi menunjukkan kekuatan, di sisi lain melemahkan norma internasional yang selama ini dijadikan rujukan bersama. Pertanyaannya, apakah runtuhnya Doktrin Monroe justru mempercepat realisasi visi hegemoni Xi Jinping di Asia, dan bagaimana seharusnya Indonesia membaca perubahan ini?
Doktrin Monroe dan Warisan Intervensi
Doktrin Monroe, diumumkan Presiden James Monroe pada 1823, bertujuan mencegah campur tangan kekuatan Eropa di Belahan Barat. Dalam praktiknya, doktrin ini berkembang menjadi legitimasi intervensi AS terhadap negara-negara Amerika Latin, melalui operasi militer, dukungan kudeta, hingga sanksi ekonomi. Kuba, Nikaragua, Panama, dan Chili menjadi contoh bagaimana doktrin tersebut diterjemahkan dalam kebijakan keras demi menjaga kepentingan strategis Washington.
Kasus Venezuela menghadirkan anomali geopolitik. Selama lebih dari satu dekade, negara ini menjadi medan persaingan kekuatan besar. Rusia menanamkan investasi puluhan miliar dolar dalam bentuk persenjataan canggih, seperti jet tempur Su-30 dan sistem pertahanan udara S-300. China, di sisi lain, menyalurkan pinjaman sekitar 10 miliar dolar AS untuk infrastruktur dan pembelian minyak, memperdalam ketergantungan ekonomi Caracas pada Beijing. Meski ekonomi Venezuela menyusut drastis—sekitar 70–75 persen sejak 2013 akibat sanksi AS—rezim Maduro bertahan melalui jalur perdagangan alternatif non-dolar.
Operasi Delta Force AS, disertai pengerahan kapal induk USS Gerald R Ford di Karibia, menandai eskalasi baru. Penahanan Maduro atas dakwaan narkoterorisme di New York dan klaim Presiden Donald Trump bahwa AS akan “mengendalikan” Venezuela selama masa transisi, termasuk rencana “karantina” minyak untuk kepentingan korporasi energi, memperkuat persepsi bahwa Doktrin Monroe kini dijalankan dalam versi yang lebih kasar dan terbuka.
Ironi Geopolitik: Keuntungan Strategis bagi Beijing
Paradoksnya, fokus AS di Amerika Latin justru menguntungkan China. Ketika Washington mengalihkan perhatian dan sumber daya, Beijing meningkatkan tekanan militer dan diplomatik di Asia Timur. Latihan militer besar-besaran di sekitar Taiwan pada akhir Desember 2025—termasuk peluncuran misil dan simulasi pengepungan pulau—menjadi sinyal tegas. China secara terbuka menyoroti sistem HIMARS Taiwan sebagai ancaman, sekaligus membenarkan respons militer skala besar.
Presiden Xi Jinping mempromosikan narasi “nilai Asia” dan diplomasi bertetangga baik, namun praktik di lapangan menunjukkan penggunaan kekuatan ekonomi dan militer untuk menekan negara-negara kawasan. Jepang menghadapi tekanan ekonomi, sementara klaim “sembilan garis putus-putus” di Laut China Selatan terus dipertahankan meski bertentangan dengan hukum laut internasional.
Analis strategi Rush Doshi menilai bahwa erosi norma anti-kekerasan oleh adidaya justru menciptakan lingkungan yang menguntungkan China. Pernyataan terkenal mantan Menteri Luar Negeri China pada 2010—“China besar, negara lain kecil”—mencerminkan mentalitas hierarkis yang kini memperoleh pembenaran de facto. Rusia, yang memandang ekspansi NATO sebagai preseden bagi tindakannya sendiri, tampak tak berdaya memberikan dukungan nyata kepada Maduro karena keterikatannya dalam konflik Ukraina.
Asia Tenggara di Persimpangan Strategis
Bagi Asia Tenggara, dinamika ini bukan sekadar tontonan global, melainkan realitas yang berdampak langsung. Kawasan ini menjadi titik temu kepentingan ekonomi, jalur perdagangan vital, dan arena persaingan pengaruh antara AS dan China. Ketika AS menunjukkan kecenderungan bertindak unilateral, dan China semakin asertif, ruang manuver negara-negara ASEAN menyempit.
Klaim sepihak di Laut China Selatan, intensifikasi militerisasi, serta diplomasi ekonomi berbasis ketergantungan utang menempatkan negara-negara Asia Tenggara dalam dilema: menjaga hubungan ekonomi dengan China tanpa mengorbankan kedaulatan dan stabilitas regional. Runtuhnya konsensus global tentang penghormatan terhadap norma internasional memperbesar risiko salah perhitungan dan eskalasi konflik.
Posisi Indonesia: Netralitas Aktif sebagai Pilar
Indonesia merespons operasi AS di Venezuela dengan menyatakan keprihatinan mendalam dan menyerukan pengendalian diri, dialog, serta penghormatan terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan kedaulatan negara. Sikap ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif yang telah lama dianut.
Dalam konteks China, Indonesia menegaskan penolakan atas klaim Beijing di Natuna Utara karena bertentangan dengan UNCLOS 1982. Namun, Jakarta tetap membuka ruang kerja sama maritim dan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam kesepakatan bilateral saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke China. Presiden Prabowo menekankan komitmen menjaga hak kedaulatan Indonesia, sembari mendorong percepatan finalisasi Code of Conduct (CoC) ASEAN–China yang ditargetkan tercapai pada 2026, bertepatan dengan keketuaan Filipina di ASEAN.
Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan yang sulit namun krusial: tidak terjebak dalam politik blok, tetapi juga tidak abai terhadap kepentingan nasional dan hukum internasional.
Implikasi bagi Perdamaian Global
Runtuhnya Doktrin Monroe dalam praktiknya memperlihatkan pergeseran menuju dunia multipolar yang belum matang. Politik pembagian zona pengaruh berisiko memicu kompetisi kekerasan antar-adidaya, melemahkan institusi multilateral, dan mengikis kepercayaan terhadap norma internasional. Perdamaian global tidak dapat dipertahankan melalui aksi unilateral atau logika “siapa kuat dia menang”.
Sebaliknya, dialog multilateral, penguatan hukum internasional seperti UNCLOS, serta mekanisme regional yang inklusif menjadi kunci stabilitas. ASEAN, dengan segala keterbatasannya, tetap merupakan platform penting untuk meredam konflik dan membangun konsensus kawasan.
Penutup: Pelajaran Strategis bagi Indonesia
Erosi Doktrin Monroe menandai berakhirnya ilusi bahwa satu kekuatan dapat mengatur tatanan global tanpa konsekuensi. Bagi China, situasi ini membuka peluang memperluas pengaruh; bagi kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, tantangannya adalah mengelola risiko tanpa kehilangan otonomi strategis.
Pesan moralnya jelas: Indonesia perlu terus memperkuat netralitas aktif, konsistensi pada hukum internasional, dan kepemimpinan regional melalui ASEAN. Di era ketidakpastian global, kedaulatan dan stabilitas tidak dijaga dengan memilih pihak, melainkan dengan prinsip, diplomasi cerdas, dan keberanian mempertahankan kepentingan nasional di tengah pusaran geopolitik dunia.

 1 month ago
57
1 month ago
57