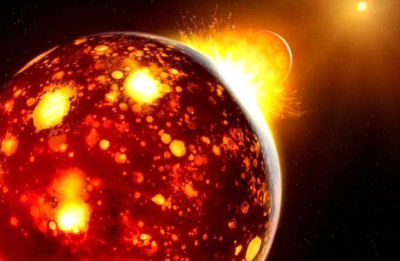Andi Subhan Husain, PhD Researcher in International Development Studies, Chulalongkorn University / Ketua PCI Muhammadiyah Thailand
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Di era ketika dunia diukur dari likes dan algoritma, mungkin sebagian mempertanyakan: siapakah yang layak disebut sebagai pahlawan hari ini? Di masa lalu, jawabannya jelas bahwa mereka yang mengangkat senjata melawan penjajahan.
Tapi di zaman ini, sosok pahlawan justru sering kali lahir dari mereka yang bekerja dalam senyap: diplomat yang menegosiasikan perdamaian tanpa sorotan, peneliti yang berjibaku dengan penyakit menular, dokter di pelosok negeri, atau pendidik yang setia membimbing generasi meski ruang penghargaan bagi mereka kian terbatas dan kerap terabaikan.
Menafsirkan Ulang Makna Pahlawan
Dalam pandangan Islam, pahlawan sejati bukan hanya mereka yang gugur di medan perang, tapi siapapun yang menegakkan kebenaran dengan kesabaran. Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” (HR. Ahmad)
Hadits ini sederhana, tapi revolusioner karena menempatkan kepahlawanan dalam kerja kemanusiaan, bukan sekedar kemenangan fisik. Maka guru yang membentuk nalar kritis murid-muridnya, diplomat yang menjaga perdamaian atau peneliti yang menemukan solusi pangan untuk dunia kelaparan, hakikatnya melanjutkan spirit jihad kemanusiaan itu.
Benedict Anderson (2006) menyebut bangsa sebagai imagined community, namun di Dunia Selatan (Global South), imajinasi kebangsaan itu juga dibentuk oleh luka sejarah kolonialisme. Dari Afrika hingga Asia Tenggara, kepahlawanan sering lahir bukan dari kekuasaan, tapi dari tekad melawan penindasan dan menjaga martabat manusia.
Tokoh seperti K.H. Ahmad Dahlan di Indonesia yang melawan kebodohan dan kemiskinan dengan membuka ruang pendidikan modern berbasis Al-Qur’an, dan Nyai Siti Walidah yang menggerakkan perempuan melalui Aisyiyah agar berilmu, berakhlak, dan berdaya tanpa menyalahi fitrah. Mereka tidak menentang tradisi agama, tetapi menafsirkan dakwah sebagai kerja kemanusiaan; menolong yang lemah, mengajarkan ilmu, dan memperluas kasih sayang.
Nasionalisme sebagai Ibadah Sosial
Menghormati pahlawan bukan hanya soal upacara atau penghargaan, tapi bagaimana kita menghidupi nilai yang mereka perjuangkan. Dalam Islam, cinta tanah air bukan slogan kosong, ia bagian dari ‘amal shalih jika diorientasikan untuk menegakkan keadilan (adl) dan kemaslahatan (maslahah).
Frantz Fanon (1963) mengingatkan bahwa dekolonisasi sejati adalah proses terus-menerus untuk memanusiakan manusia. Nasionalisme di dunia Selatan hari ini tidak lagi tentang menutup diri, tetapi bagaimana membangun kedaulatan dalam sistem global yang masih timpang. Maka peneliti lokal yang menolak data manipulatif, aktivis yang membela kaum buruh, atau ulama yang menulis tentang etika perdagangan halal yang adil, semuanya bagian dari jihad modern untuk memerdekakan manusia dari penindasan.
Soeharto, Gus Dur, dan Tafsir Kepahlawanan yang Kompleks
Ketika muncul wacana menjadikan Soeharto dan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Pahlawan Nasional, banyak orang terbelah. Tapi saya melihat perdebatan ini sebagai refleksi bangsa yang sedang belajar menilai masa lalunya secara jujur.
Soeharto mungkin mewariskan otoritarianisme, tetapi juga stabilitas ekonomi. Gus Dur membawa kebebasan dan toleransi, tetapi juga membuka ruang perdebatan yang belum selesai. Dalam Islam, penilaian terhadap manusia selalu bersifat proporsional: “Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” (QS. Al-Ma’idah: 8).
Kepahlawanan, dengan demikian, bukan kemurnian tanpa cela, melainkan keberanian menanggung konsekuensi dari pilihan-pilihan sejarah. Bangsa yang matang adalah bangsa yang mampu mengenang dan mengkritik dalam waktu yang sama.
Mereka yang Bekerja dalam Sunyi
Di kota Bangkok, saya menyaksikan bagaimana kepahlawan itu hadir dalam bentuk senyap namun bermakna. Saya bertemu sosok diplomat yang juga aktif mengurus masjid, bekerja membela martabat manusia dengan penuh kesadaran, tanpa sorotan kamera. Paulo Freire (1970) menyebutnya praxis: tindakan sadar yang berupaya mengubah struktur penindasan. Di tangan orang-orang yang siap bekerja meski tanpa riuh tepuk tangan dan kamera, saya melihat wajah Islam yang rahmatan lil-‘alamin, keberanian bekerja dalam sepi demi kemaslahatan orang lain, menjadikan kemanusiaan sebagai inti dari tugas negara dan ibadah.
Dari ruang riset, mimbar masjid, hingga komunitas diaspora, juga bisa ditemukan bentuk nasionalisme yang tulus, meski pelan, mereka ikut menyalakan cahaya masa depan bangsa.
Di negeri rantau saya bertemu dan belajar dari para guru dengan wajah-wajah yang sederhana tapi menyimpan keteguhan luar biasa. Ada pelajar Indonesia yang menempuh studi doktoral sambil tetap meluangkan waktu untuk mengaji. Ada dosen dari kampus ternama yang meneliti ketahanan pangan dan perubahan iklim. Ada dokter yang meneliti DNA dan kesehatan masyarakat, berharap temuannya bisa memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di negeri asal. Ada peneliti farmasi yang berjuang menemukan formula halal dan terjangkau bagi pasien berpenghasilan rendah. Ada pula profesional muda yang bekerja di dunia media, menulis dan memproduksi narasi-narasi positif tentang kemanusiaan dan kebersamaan, di tengah arus informasi yang penuh sensasi.
Saya memahami makna kepahlawanan hari ini, bukan lagi pertempuran dengan senjata, melainkan kesetiaan pada panggilan kebaikan. “Fastabiqul Khairat”. Para peneliti, tenaga medis, guru, aktivis, dan diplomat di sekitar saya mungkin tidak dikenal publik, tapi melalui ilmu, ketekunan, dan doa, mereka menghidupkan nilai-nilai Islam tentang amal dan rahmah. Inilah wajah baru kepahlawanan: tidak selalu viral, tapi vital.
Kepahlawan dalam Sunyi yang Istiqamah
Hiruk pikuk dunia, khususnya sosial media yang selalu mempertontonkan kegemerlapan, sesungguhnya kepahlawanan sering kali tumbuh dalam kesunyian yang tak banyak disadari. Ia hadir meski tanpa jutaan followers medsos, ia hadir dalam Langkah-langkah kecil yang konsisten: seorang guru yang tetap mengajar meski di ruang kelas yang sederhana, peneliti yang setia merawat data meski fasilitas terbatas, atau tenaga pengabdian yang terus bekerja dengan tulus kendati penghargaan belum sepadan dengan jerih payah. Kita menyebut mereka “pahlawan tanpa tanda jasa” sebuah ungkapan yang indah, namun juga patut direnungi agar tidak berhenti sebagai romantisasi, melainkan mendorong perhatian yang lebih nyata terhadap kesejahteraan dan martabat mereka.
Bangsa yang memberikan penghargaan kepada guru dan pahlawannya bukan hanya melalui narasi heroik atau seremoni penghormatan, tetapi melalui keberpihakan yang konkret: memastikan ruang yang adil bagi mereka untuk tumbuh, dihargai, dan dilindungi. Di ruang-ruang sunyi seperti kelas, laboratorium, masjid, dan kantor layanan publik, kita semua meyakini masih ada sosok pahlawan yang bekerja penuh ketekunan dan jujur tanpa mencari sorotan.
Mereka bekerja untuk menebar manfaat, menjaga keadilan, dan merawat kehidupan. Mereka tidak menuntut tepuk tangan; cukup melihat orang lain tumbuh sudah menjadi ganjaran tersendiri. Merekalah cahaya kecil yang tak padam, bahkan ketika tidak ada yang melihat.

 2 months ago
79
2 months ago
79