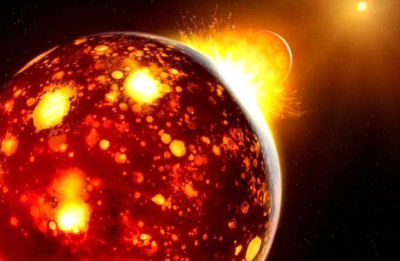Foto ilustrasi Catatan Cak AT, Beton, Baja dan Balok yang Tobat. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA)
Foto ilustrasi Catatan Cak AT, Beton, Baja dan Balok yang Tobat. (Foto: Dok RUZKA INDONESIA) RUZKA-REPUBLIKA NETWORK -- Kalau ada yang paling setia pada manusia sejak zaman purba, mungkin bukan pasangan hidup, tapi batu bata. Ia hadir di setiap peradaban — dari piramida Mesir, tembok Tiongkok, sampai rumah BTN yang cicilannya bikin napas sesak selama 15-20 tahun.
Tapi siapa sangka, justru benda bisu bernama beton ini diam-diam menjadi penyumbang 8% emisi karbon dunia. Ya, setiap gedung yang kita bangun, sebenarnya adalah “cerobong vertikal” yang menembakkan CO ke langit — tapi dengan gaya arsitektur minimalis dan AC sentral.
Padahal di balik semua itu, laporan kolaborasi World Economic Forum (WEF) dan Frontiers mengingatkan bahwa ada cara lain membangun tanpa merasa jadi perusak.
Menata ruang tanpa menambah kerusakan. Mereka menamainya: green concrete — beton yang bertobat, dan mulai sadar bahwa ketahanan tak harus dibayar dengan kerusakan.
Baca juga: FEB UI Beri Pelatihan Eco-Enzyme di SDN Beji Timur 1 Depok
Mari kita jujur dulu: kita semua hidup di kota yang makin abu-abu, secara warna maupun batin.
Hutan diubah jadi komplek, sawah dijadikan sirkuit, dan gedung menjulang seperti ego yang ingin memecahkan langit. Beton jadi lambang kemajuan, meskipun fondasinya adalah tanah yang kehilangan kehidupan.
Tapi kini, para ilmuwan sedang mengajarkan beton untuk menyesal. Ya, menyesal karena selama ini ia memuntahkan karbon. Cara tobatnya? Dengan mengganti semen — bahan pengikat utama — dari hasil pembakaran batu kapur, menjadi bahan sisa industri, seperti abu pembakaran, limbah baja, atau bahkan serbuk kaca daur ulang.
Ada pula teknologi yang menyuntikkan CO langsung ke dalam campuran beton, menjebaknya di sana untuk selama-lamanya. Hasilnya: beton yang lebih kuat, tapi jejak karbonnya lebih ringan.
Bayangkan, suatu hari nanti, kota-kota tidak hanya menelan udara bersih, tapi menghirup dan menyimpan karbon. Bangunan bukan lagi monster rakus, tapi paru-paru baru bagi planet.
Baca juga: INTI 2025, Wondershare Berikan Solusi Perangkat Lunak Berbasiskan AI untuk Industri Kreatif
Tapi perubahan tak hanya soal bahan. Ia juga soal cara kita berpikir tentang ruang.
Dulu, arsitek berlomba membangun yang tinggi — seolah ketinggian gedung bisa menggantikan kedalaman nurani. Kini, arah baru arsitektur bukan lagi “ke atas”, tapi "ke dalam" — ke dalam tanah, ke dalam hati, ke dalam ekologi. Gedung masa depan bukan hanya hemat energi, tapi menghasilkan energi.
Atap bukan lagi tempat antena, tapi kebun surya. Dinding bukan lagi pemisah, tapi penyerap panas. Ventilasi bukan lagi akses udara, tapi jembatan kehidupan. Inilah arsitektur yang bukan hanya nyaman untuk manusia, tapi juga ramah bagi cacing, burung, dan mikroba.
Di Singapura, pemerintah mewajibkan setiap gedung tinggi menanam pohon di fasadnya. Di Belanda, ada proyek beton daur ulang yang menyimpan karbon lebih banyak daripada yang dikeluarkannya.
Di Indonesia, kita punya rumah panggung yang sudah ramah lingkungan sejak nenek moyang — ventilasi alami, kayu lestari, tanpa semen. Tapi sayangnya, kita sering lebih bangga pada gedung kaca yang memantulkan panas dan menolak cahaya.
Baca juga: Catatan Cak AT: Energi dari Langit, Listrik dari Tanah
Padahal, kalau mau jujur, “modernitas” tak selalu sejalan dengan “kebijaksanaan.” Kadang justru arsitektur tradisional lebih hijau dari desain futuristik yang katanya pintar.
Rumah adat di Toraja, Minangkabau, atau Papua tidak sekadar indah, tapi adaptif terhadap alam. Ia tahu kapan menampung air, kapan membiarkannya meresap.
Ia bukan menantang alam, tapi berdialog dengannya. Sebaliknya, arsitektur modern sering seperti anak muda yang keras kepala — ingin semua bisa dikontrol, termasuk suhu udara dan arah matahari.
Teknologi green concrete ini hanyalah simbol dari pertobatan besar yang sedang terjadi: bahwa pembangunan tidak harus berarti penghancuran. Bahwa kota masa depan tidak hanya diukur dari tinggi gedung, tapi dari rendahnya emisi. Bahwa keberadaban bukan diukur dari kemewahan ruang, tapi dari kejujuran bahan.
Baca juga: Kementerian Komdigi Ingin Anak Melek Digital tetapi Tetap Aman dan Sehat
Kita butuh arsitektur yang berjiwa — yang tahu bahwa ruang bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk udara, tanah, dan air. Kota yang baik bukan yang megah, tapi yang bisa bernapas. Gedung yang baik bukan yang paling kuat menahan gempa, tapi yang paling lembut menjaga bumi.
Barangkali nanti, anak-anak kita akan berjalan di trotoar dari beton yang menyerap karbon, bukan menyemburkannya. Mereka akan berlindung di bawah gedung yang memanen hujan, bukan membuangnya ke got. Dan mereka akan tinggal di rumah yang dingin bukan karena AC, tapi karena desain yang cerdas — rumah yang "berhati", bukan hanya ber-IMB.
Mungkin di situlah makna sejati dari kata "modern": bukan sekadar baru, tapi "membaik."
Kalau dulu beton adalah simbol kerasnya peradaban, kini ia sedang belajar menjadi lembut. Dan kalau manusia mampu mengajari batu untuk bertobat, maka tak ada alasan bagi manusia sendiri untuk terus keras kepala.
Karena di ujung semua pembangunan, bumi tidak menuntut kita jadi megah — ia hanya ingin kita jadi bijak. (***)
Penulis: Cak AT – Ahmadie Thaha/Ma’had Tadabbur al-Qur’an, 30/10/2025

 3 months ago
125
3 months ago
125