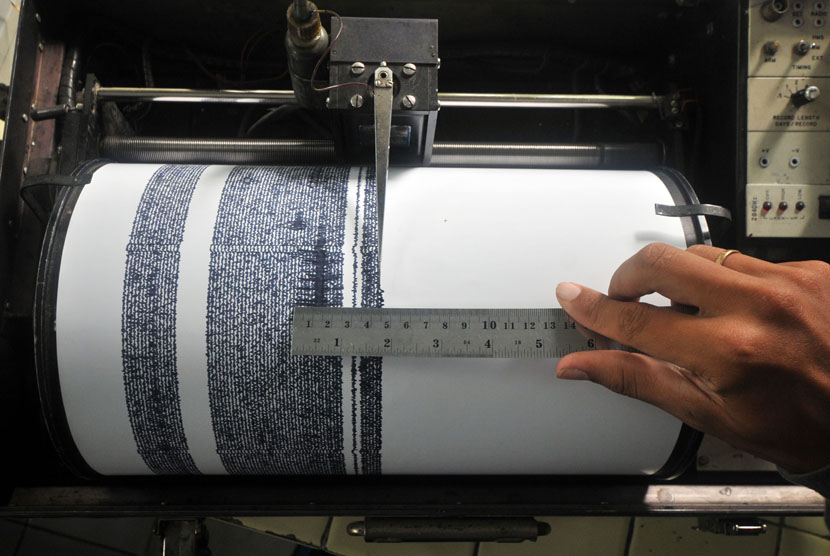Asrul Putra Bastari
Asrul Putra Bastari
Agama | 2025-05-16 14:01:52
 *umat islam kini cenderung membanggakan masa lalunya, tanpa menyadari kemunduran yang terjadi di masa kini
*umat islam kini cenderung membanggakan masa lalunya, tanpa menyadari kemunduran yang terjadi di masa kini
Sudah sejak lama kita diajarkan bahwa penyebaran Islam adalah proses yang damai, penuh keteladanan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual. Kita bangga dengan narasi bahwa para saudagar Muslim menyebarkan Islam lewat jalur dagang, tanpa pedang, tanpa darah. Tapi seiring waktu dan membaca ulang sejarah dengan lebih jernih, saya mulai bertanya: apakah benar semuanya sesuci itu?
Ketika menelusuri sejarah Kekaisaran Ottoman misalnya, salah satu simbol kejayaan Islam yang sering dibanggakan-banggakan. saya justru menemukan catatan tentang kekerasan, penjajahan, dan dominasi atas wilayah-wilayah Eropa. Tentu tidak jauh berbeda dari apa yang dilakukan oleh bangsa Eropa terhadap Asia dan Afrika. Dalam konteks ini, saya jadi bertanya: apa benar hanya Barat yang rakus? Apakah kekuasaan Islam di masa lalu betul-betul murni karena dakwah dan keimanan? Atau justru punya motif yang serupa: gold, glory, dan gospel?
Kesadaran itu menuntun saya ke refleksi yang lebih dalam: bisa jadi, kita selama ini terlalu memutihkan sejarah Islam sendiri karena terbuai oleh glorifikasi. Kita lebih cepat menuduh Barat sebagai penjajah, namun enggan mengkritisi ekspansi Islam yang juga membawa kekerasan. Kita menjunjung satu narasi tunggal yang indah, tanpa menyisakan ruang untuk mengakui bahwa penyebaran agama apa pun itu, seringkali bercampur antara ideal dan hasrat kekuasaan.
Umat Islam hari ini kerap membanggakan kejayaan masa lalu, ketika Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia, ketika tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi memimpin peradaban dengan pemikiran brilian. Namun kebanggaan itu sering kali menjadi semacam tirai yang menutupi kenyataan pahit: bahwa umat Islam kini justru tertinggal dalam inovasi, ilmu pengetahuan, dan budaya berpikir kritis. Kita terlalu asyik hidup dalam bayang-bayang kemegahan sejarah, tanpa benar-benar menyadari kehampaan intelektual.
Dari sana, muncul satu ironi yang lebih terasa dalam kehidupan kita sehari-hari: fanatisme yang dibungkus oleh pengkultusan Arab. Di banyak komunitas Muslim Indonesia, menjadi Islam berarti menjadi Arab. Bukan hanya dalam bahasa dan pakaian, tapi juga dalam pola pikir dan standar kesalehan. Orang dianggap lebih islami jika menyelipkan kata-kata Arab dalam percakapan, mengenakan gamis ala Timur Tengah, atau mengidolakan tokoh-tokoh dari sana.
Lebih dari itu, cerita-cerita tentang para leluhur dari Arab seringkali dibungkus dengan kisah-kisah luar biasa, seolah-olah mereka makhluk setengah malaikat: bisa terbang, berpindah tempat dalam sekejap, bahkan membaca isi hati manusia. Bahkan kisah nabi pun kalah hebat dengan cerita-cerita itu. Sementara ulama-ulama lokal yang membumikan Islam dengan pendekatan budaya, seperti para wali di Jawa atau tokoh adat di Sumatra, justru tersisihkan dari narasi besar. Kehebatan Islam seakan-akan hanya boleh lahir dari jazirah Arab, bukan dari tanah kita sendiri.
Ironisnya, hal semacam ini pernah pula terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Kaum Quraisy sangat memuja kisah kehebatan leluhur mereka, bangga pada garis keturunan, pada keagungan nama suku, dan kisah-kisah heroik yang dilebih-lebihkan tentang nenek moyang. Tapi Nabi tidak menguatkan glorifikasi itu. Justru beliau hadir membawa pesan tauhid yang membongkar kultus terhadap manusia, menolak fanatisme kabilah, dan mengajak manusia untuk tidak lagi menjadikan keturunan atau asal-usul sebagai tolok ukur kebenaran. Bahkan dalam khutbah terakhirnya, beliau menegaskan bahwa tidak ada keutamaan antara Arab dan Ajam (non-Arab) kecuali karena takwa. Di situlah letak revolusi Islam: bukan pada budaya Arabnya, melainkan pada semangat pembebasannya.
Sayangnya, semangat pembebasan itu perlahan terkikis oleh cara sebagian kita memaknai agama hari ini. Kita menilai kesalehan dari seberapa "Arab" seseorang, bukan dari akhlaknya. Kita bangga menyebut diri sebagai umat Nabi, tapi justru melestarikan pola pikir jahiliyah yang beliau perangi yaitu fanatisme pada simbol, bukan nilai.
Fanatisme lahir dari glorifikasi buta, dan sayangnya glorifikasi itu terus diwariskan dari mimbar ke mimbar, dari pesantren ke media sosial. Kita kehilangan keberanian untuk bertanya, untuk menimbang, dan untuk merdeka secara spiritual.
Padahal, Islam tidak pernah menuntut kita menjadi Arab. Islam hanya menuntut kita menjadi pribadi yang adil, jujur, berempati, dan berpihak pada kebenaran. Maka ketika kita menyempitkan Islam hanya pada budaya tertentu, kita sebenarnya sedang mengerdilkan ajaran yang seharusnya bersifat rahmatan lil ‘alamin.
Sudah saatnya kita menggugat fanatisme yang mengakar. Islam bukan milik Arab. Islam adalah milik semua manusia yang mau tunduk kepada kebaikan, keadilan, dan cinta kasih. Ia bisa hidup di mana saja: di padang pasir, di rimba, di desa, di kampus, bahkan di tengah masyarakat multikultural. Islam akan tetap Islam, selama nilai-nilainya dijunjung, bukan karena jubah, bukan karena bahasa, bukan karena silsilah.
Akhirnya, sebagai Muslim yang hidup di Indonesia, saya hanya ingin beragama dengan waras: mencintai Islam tanpa harus membenci nalar, mencintai Rasul tanpa membenci tanah air, mencintai kebenaran tanpa harus menutup mata pada sejarah yang kompleks. Karena hanya dengan kesadaran itu, saya percaya, kita bisa membangun umat yang bukan hanya taat, tapi juga merdeka.
Disclaimer
Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

 1 month ago
51
1 month ago
51